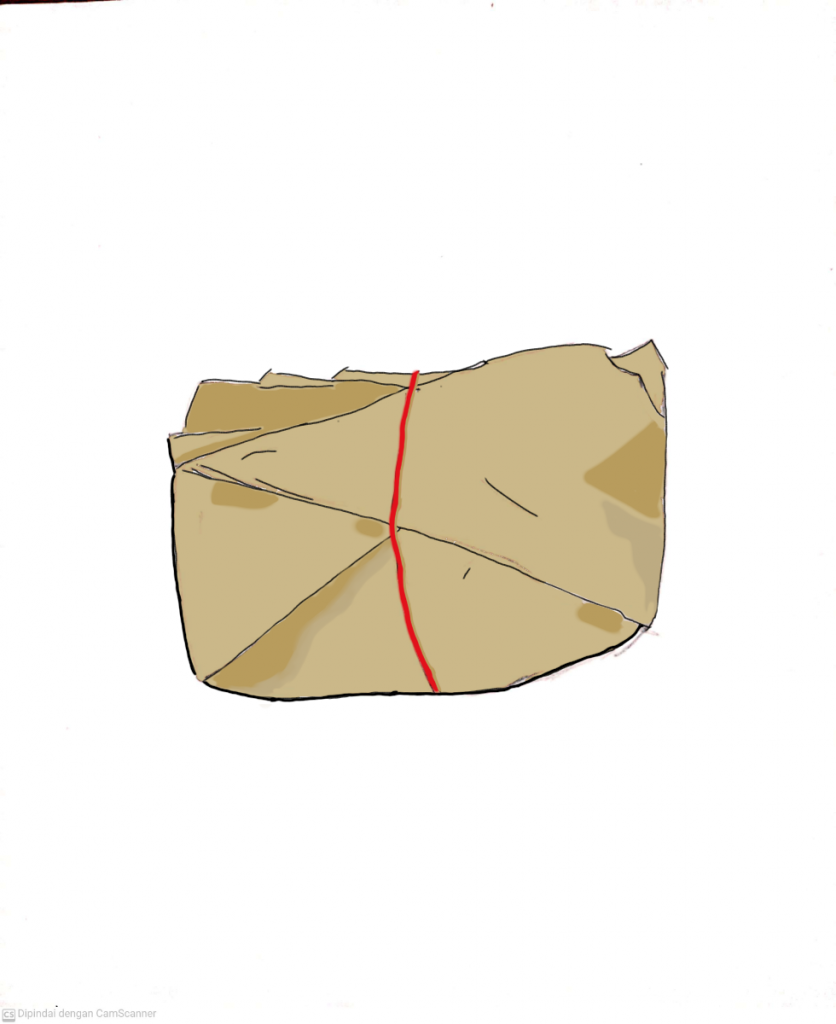Orang-orang itu berkerubung. Seketika suasana yang mencekam membeku, setelah teriakan panjang dan istighfar bersahutan, mereka mulai bergerak dan mendekati mayatnya yang berlumuran darah. Tak ada yang menyangka ia akan mengalaminya. Tak sebersitpun pemikiran bahwa ia akan berada disana dan semua orang memperhatikannya. Hanya itulah pertama kalinya ia dipandang setelah hampir bertahun-tahun lamanya, hidup sejajar dengan anjing buluk dan tikus besar di Jakarta. Sedetik itu segalanya menjadi nyata. Stasiun kembali pada mula, ramai dan berjalan seperti sediakala. Tak ada lagi yang memedulikannya setelah semua peristiwa yang terjadi bagai kedipan mata. Orang-orang mulai kembali pada aktivitasnya masing-masing, hanya petugas stasiun yang mulai bergerak membereskan bekas mayatnya. Tak perlu reka adegan, tak perlu juga rekontruksi, tak ada penumpang yang dimintai keterangan. Sebagaimana mereka menganggap mayat itu tidak penting, seperti itu jugalah mereka menganggap kematian itu sebagai sesuatu yang tidak perlu dibesar-besarkan. Tetek bengek macam itu hanya dibutuhkan bila seseorang yang penting, seperti pejabat atau artis yang secara mengejutkan telah meninggal.
“Haduh, kenapa pula orang ini disini. Kalau mau cari tempat buat mati di laut saja, lumayan buat makan ikan. Bikin repot saja.” Petugas itu bersungut-sungut membereskan bekas kejadian, dan petugas lain yang membawa pel tampak tenang.
“Tak usahlah kau ributkan hal begini. Kasihan juga dia. Kita makamkan di tempat yang layak.”
“Dimakamkan? Apa kau bilang? Siapa yang bayar? Dia tidak punya keluarga. Siapa yang mau mengunjungi dan merawat makamnya?”
“Kita tanyakan pada Pak Kepala. Dia kan’ punya banyak duit. Dia pasti mau membantu orang ini. Lagipula, masa kita biarkan mayatnya seperti ini? Mau kita taruh dimana selain dimakamkan? Masalah biaya toh juga bukan kita yang turut andil…”
Begitulah perdebatan macam yang justru terjadi saat ia meninggal. Simpati hanya didapatkan dari seseorang yang telah lama mengenalnya. Ya, petugas dengan kain pel itu. Mayat itu sendiri bernama Rustam. Ia adalah gembel gangguan kejiwaan, yang telah bertahun-tahun akrab dengan kota besar seperti Jakarta. Telah lama ia mondar mandir di stasiun, selain pekerjaannya yang suka cari sisa makanan di pasar. Secara mengenaskan Rustam ditemukan pagi tadi tewas tertabrak kereta. Sungguh malang nasib lelaki tua itu. Usianya sudah memasuki senja, sementara tubuhnya yang kurus kering semakin membuatnya tampak tua.
Petugas tadi sering memergoki Rustam berjalan-jalan di stasiun itu, tak sampai hati mengusirnya karena ia selalu teringat bapaknya yang sudah meninggal. Bapaknya sama kurusnya dengan Rustam, walaupun masih hidup lebih baik ketimbang Rustam. Tak jarang ia memberikan bekal atau jatah makanannya untuk Rustam, yang selalu disambut ceria oleh Rustam sembari mengucapkan terimakasih per suapan yang dimakannya. Pernah pula suatu ketika, saat sedang bulan puasa dan waktunya berbuka, petugas yang baik itu memberikan bekalnya kepada Rustam, sementara ia sendiri menahan perih lapar sampai tiba waktunya pulang. Tak seperti biasa, Rustam tidak ceria menerimanya, ia memandang petugas itu dengan sedih dan menyisihkan lebih dari separuh bekal itu untuk sang petugas. Petugas itu menahan airmatanya sembari menjelaskan pada Rustam bahwa ia lebih pantas menerima bekal itu, sebab Rustam sendiri sudah terlalu sering menahan lapar dan haus. Rustam merengek-rengek dengan keras sampai petugas itu mau menerima pemberiannya. Begitulah, kedua orang itu makan bersama selama petang, didahului alunan adzan dan disaksikan matahari terbenam.
***
Aku sendiri telah mendengar kematian Rustam dari sahabat-sahabatku di pasar. Mantan badut yang ditakuti anak-anak itu, yang menceritakannya padaku. Ia prihatin katanya sebab Rustam adalah teman dekatku. Mantan badut itu tidak setua diriku, ia baru empat puluh lima tahun dan sering didapati tertawa-tawa sendiri di pojok kios jagal ayam. Aku tidak begitu tahu bagaimana ceritanya ia bisa sampai gila, yang jelas tidak jauh dari sangkut paut utang piutang.
Aku ingin segera bergegas ke stasiun, untuk mendengar kabar langsung dari sang petugas, tapi aku agak malu. Sebelum aku tiba mereka pasti langsung mengusirku. Maklumlah, mengais makanan di tong sampah depan pos polisi saja diusir apalagi memberanikan diri bertanya pada orang waras. Aku sebenarnya tak pernah tahu apa alasan mereka menyebutku gila, karena sejujurnya kadang aku melakukan sesuatu langsung dari lubuk hatiku sendiri. Di tengah jalan misalnya, saat aku ingin berjumpa dengan kawanku, aku langsung memikirkannya dan tiba-tiba ia berada di depanku, jadi aku berbincang dengannya. Jika orang bilang aku gila karena berbicara sendiri, bukankah mereka juga ikut gila karena sering berbincang sendiri dengan benda kecil yang penuh tombol itu? Ah, pusing aku. Tak tahulah apa benda itu. Yang penting itu juga bukan sesama manusia. Mana bisa bicara dengan benda.
Aih, sedih sekali aku setiap kali mengingat Rustam sahabatku. Kami sering kali berjalan melewati SMA setiap hari Senin. Ia bercerita padaku bahwa cucunya pasti sekarang telah jadi pengibar bendera saat upacara. Ia ingin sekali suatu waktu bisa menontonnya mengibarkan bendera, karena entah mengapa, setiap kali bendera merah putih itu berkibar, ada gelora yang tiba-tiba memuncak dalam darahnya, dan jiwanya serasa bebas ikut berkibar bersama bendera itu, dan tak jarang deg-degan pula hatinya mendengar lagu Indonesia Raya berkumandang.
Rustam dan aku adalah salah satu saksi saat bendera itu pertama berkibar. Aku selalu ingin menangis saat mengingatnya. Rustam adalah salah satu pemuda penculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok. Tidak, Rustam tidak mengikuti rapat dan semacamnya, atau menjadi salah satu tokoh utama penculikan itu. Ia hanya bagian jaga di sekitar lokasi, dan aku sendiri tidak ikut penculikan itu sebab aku sakit saat itu. Sungguh bangga aku pada Rustam. Pada awalnya ia berjanji takkan meninggalkanku, tapi aku bersikeras menyuruhnya pergi.
Rustam juga salah satu pasukan pembawa bambu runcing saat menghadapi pasukan Jepang. Ia adalah salah satu orang yang terjun dalam berbagai upaya pertempuran, dan kebetulan juga ia ikut melibatkan diri atas peristiwa Surabaya. Ia getol sekali berjuang untuk kemerdekaan. Ia tidak mengincar apapun demi apapun. Ia hanya melakukan tugasnya sebagai rakyat Indonesia, dan semata-mata yang ia inginkan hanyalah kemerdekaan bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia.
Bagaimana aku menjelaskan kepadamu, kawan, tentang asal mula bagaimana Rustam bisa jadi seperti sekarang, dengan kondisi yang sangat menyedihkan sepertiku juga? Setelah proses kemerdekaan selesai, Rustam hidup bahagia dengan keluarganya. Ia akhirnya menikah pada 1950 dan dikaruniai lima orang anak. Semua menjadi semakin sulit setelah memasuki 80-an. Ia tidak punya pekerjaan, dan anak-anaknya satu persatu meninggalkannya, tanpa ada kabar. Ia berusaha membuat dan menjual mainan, tapi tidak laku, berusaha mendapatkan tunjangan hidup bagi veteran, namun ia harus menunggu bertahun-tahun dan menyiapkan berbagai macam tetek bengek yang rumit. Masalah semakin runyam saat istrinya akhirnya meninggal dalam kondisi miskin. Rustam kehilangan segalanya, dan ia terlalu larut dalam dukanya akibat segalanya yang telah ia perjuangkan kini telah mengkhianatinya—anak-anaknya, istrinya yang telah meninggalkannya (walaupun itu diluar kekuasaannya) dan bahkan kemerdekaan yang telah merenggut masa mudanya untuk berjuang, semuanya telah membuatnya merasa sia-sia. Ia mulai menangis untuk waktu yang sangat lama, dan setelah menyadari bahwa airmatanya telah habis, ia mulai menertawakan semua masalah dalam hidupnya. Kehilangannya, pengkhianatan, kesulitan, kemiskinan, kepedihan, kesepian, semuanya telah merenggut berbagai kebahagiaan dalam hidupnya. Ingin rasanya ia memutar kembali waktu dari awal saat ia mempunyai hal untuk dikerjakan, teman untuk berbagi hidup, dan anak-anaknya yang masih lucu tanpa dosa. Ia mencoba memainkan mainannya yang terlihat sama menyedihkannya dengan dirinya, dan ia mulai menyadari bahwa ia telah mempermainkan dirinya sendiri. Semua hanyalah komedi dan tontonan yang asyik dipermainkan. Ia berusaha menangisi kebahagiaan dan menertawakan kesedihan. Ia sudah tak percaya pada adanya kebahagiaan dan ia percaya bahwa kesedihan adalah hidupnya, dan mungkin, sedih adalah dirinya. Ia terseok dalam lembah kekelaman dalam hidupnya, dan ia telah tenggelam dalam lumpur isap imajinasi dirinya sendiri.
Aku sendiri? Jangan tanya. Hidup merana ditinggal anak istri yang tak sudi mempunyai seorang suami dan bapak yang miskin, bekas veteran yang tak diakui pula.
Sering kubertanya pada malam, apakah benar yang dirasakan oleh Rustam? Apakah benar bahwa pada dasarnya aku adalah kesedihan itu sendiri?
***
Karena aku adalah satu-satunya yang dipunyai Rustam, dan begitupun Rustam terhadapku, aku jadi memberanikan diri berangkat ke stasiun. Aku bertemu dengan seorang petugas dan ia menanyai apa kepentinganku disini, sambil melirik ke baju gembelku yang dirubungi lalat.
“Hahaha…”aku tertawa. “Itu…”aku menunjuk rel kereta. “Betul teman saya mati disana?”
Petugas itu mengiyakan dan mencibir. “Oh, pantesan. Kamu temannya to. Iya, dia mati disana. Kamu pengin juga? Jangan buat kita repot. Pergi sana!”
“Loh! Jangan! Saya cuma kepingin tahu…”
Petugas itu mengenggam lenganku erat dan mendorongku dengan kasar keluar stasiun, dan aku hanya mengaduh sambil mencoba melepaskan diri. Tak ada gunanya. Simpati bagi orang sepertiku hanyalah sebuah angan. Tak ada yang peduli. Aku berjalan lunglai sembari keluar stasiun, dan duduk-duduk di depan tanaman rambat.
Tiba-tiba saja, suasana sekitarku terasa teduh. Aku mendengar suara langkah kaki. Saat kudongakkan kepala, aku seperti melihat malaikat!
Malaikat itu mendekat. Wajahnya bercahaya dan bajunya terlihat gagah. Ia sangat tampan dan terlihat sangat baik. Ia benar-benar seperti turun dari surga. Ia diliputi cahaya yang berkilau-kilau dan aku tak pernah melihat orang seperti ia. Mungkin ialah orang yang pernah diceritakan Rustam kepadaku. Orang yang selalu memberinya makanan dan mendengarkan ceritanya. Orang yang pernah membawakannya selimut dan tidak pernah berbuat kasar kepadanya. Orang yang membagi bekalnya saat seharusnya ia menikmatinya untuk berbuka puasa. Orang terbaik yang pernah ia temui dalam hidupnya! Ini dia! Dia pasti orang itu! Akupun memberanikan diri bertanya kepadanya, dan bahkan aku tak dapat menahan senyumku. Begitukah? Sebegitu indahnyakah orang baik terlihat di mata orang sepertiku?
Orang baik itu memberitahukan kepadaku alamat pemakaman Rustam, dan aku berseri-seri mendengarnya. Ia juga memberikanku nasi bungkus yang tadi dibelinya, dan aku menerimanya dengan sungkan, bahagia, juga dengan rasa syukur.
Aku bergegas menuju pemakaman itu. Aku mencari-cari nisan bertuliskan nama sahabatku dan akhirnya menemukannya.
“Ah ya! Aku tahu mengapa kamu begitu betah tinggal di stasiun itu, Tam! Aku paham! Aku telah bertemu dengannya, Tam! Orang yang kamu ceritakan! Bahkan aku diberi nasi bungkus! Aku sungguh senang, Tam!”
“Aku betul-betul lapar sekarang. Sulit mempercayai ada orang sebaik itu setelah apa yang telah kita lakukan pada negeri dan orang-orang yang kita perjuangkan. Ini adalah nasi bungkus kemerdekaanku, Tam. Akhirnya aku dapat makan seperti orang layak, setelah semua yang telah kita perjuangkan dan inilah harganya. Ia telah membayar lunas semua perjuangan kita, ia sudah sepatutnya dicontoh oleh seluruh orang di negeri ini, negeri yang telah merdeka.”
Aku kemudian berdiri dan ingin memberikan penghormatan terakhir untuk sahabatku, orang yang telah berjuang bersamaku, dan aku ingin mengheningkan cipta untuknya, sebagai pahlawan yang mungkin tak diakui. Aku meletakkan nasi bungkus yang masih tertutup itu di sebelah makam Rustam, yang mungkin sekarang sudah di surga menikmati nasi bungkus juga. Nanti, aku akan makan nasi bungkus itu disebelah Rustam, sembari mengobrol dan tertawa-tawa.
Namun, saat aku akan hormat padanya, mataku berkunang-kunang. Perutku terasa mulas dan seluruh sendi tulangku terasa sangat lemas. Perlahan seiring dengan aku menutup mata, aku mendengar sayup-sayup alunan nada yang sendu dan suara yang sering kudengar di upacara bendera: dengar seluruh angkasa raya memuja pahlawan negara, yang gugur remaja di ribaan bendera bela nusa bangsa…