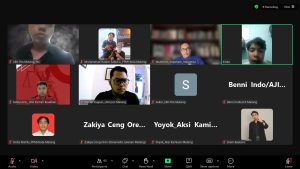Tulisan opini dari Romi Arifin dapat diakses dengan tautan ini: Opini Sastra Komoditas
Ketika membaca tulisan Romi Arifin (2023), yaitu “Sastra Komoditas” yang diterbitkan oleh LPM Perspektif, awalnya saya berpikir bahwa tulisan itu menyoroti dan mengkritisi praktik komoditasi karya sastra—menjadikan karya sastra semata-mata sebagai objek dagangan yang tidak lagi menawarkan nilai-nilai kritis seperti Max Havelaar karya Multatuli dan Tetralogi Pulau Buru oleh Pramoedya, karya yang dicontohkan oleh Arifin. Pikiran saya rupanya salah karena di akhir tulisannya, Arifin mengatakan, “Salah satu dari jalan atau usahanya adalah memproduksi karya-karya sastra yang sesuai dengan kemauan pasar, yang dengan begitu sedikit menjawab permasalahan risiko sosial para sastrawan”. Kalimat pada paragraf akhir tulisan tersebut memperlihatkan bahwa bagi Arifin, di tengah ketidakpastian, mengikuti selera pasar adalah salah satu keniscayaan. Lebih daripada itu, dengan memperhatikan dan mencermati bangunan tulisan secara menyeluruh, bagi Arifin, mengikuti selera pasar berarti meniadakan nilai, daya kritis, dan refleksi yang bisa ditawarkan oleh pengarang melalui karyanya.
Soal sastra dan komoditas bukanlah barang baru. Tugas akhir sarjana saya mengkaji sastra Melayu-Jakarta abad ke-19 yang diproduksi oleh Muhammad Bakir di Pecenongan, Batavia (Jakarta). Salah satu karyanya adalah Hikayat Wayang Pandu. Dalam konteks perubahan sosial dan sejarah sastra Melayu, Muhammad Bakir terbilang unik karena ia menyewakan naskahnya seharga 10 sen per malam. Berdasarkan temuan dan analisis, saya menyimpulkan bahwa persewaan itu memiliki tujuan ekonomi, yakni menghidupi diri dan keluarga (Windayanto, 2022). Namun, tidak berarti ia tunduk pada mekanisme pasar yang berkembang pesat di alam Melayu pada masa itu. Dia juga memiliki kepentingan ideologis, yaitu mengajak para penyewa naskahnya, Cina peranakan, untuk berhati-hati dalam membaca hikayat yang memuat cerita Mahabharata dari epik Hindu; secara ideologis, ini adalah ajakan untuk kembali pada Islam puritan (Windayanto, 2022).
Sekarang, mari kita melompat dari abad ke-19 menuju era 2010-an, sebuah lompatan sejauh satu abad lebih. Kita mengambil contoh novel 99 Cahaya di Langit Eropa (2013) karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra. Pada 2014, sejak penerbitannya pada 2011, novel ini telah dicetak lebih dari 27 kali (DetikHot, 2014). Saya yakin Anda mengenal salah satu novel Leila S. Chudori, yaitu Laut Bercerita (2017), sebuah novel sejarah yang banyak dibicarakan pada berbagai kuliah umum, diskusi, dan forum. Setelah lima tahun sejak muncul ke publik pada 2017, novel itu telah memasuki cetakan ke-48; pada pertengahan 2022, 88 ribu eksemplar telah dicetak (Hayati, 2022). Saya mencontohkan kedua novel itu sebagai representasi dari sastra perjalanan dan sastra sejarah yang bisa dikatakan berkembang pesat pada era Reformasi. Dari data tersebut, tampak bahwa novel itu mendapatkan sambutan tinggi dari masyarakat sebagai pembaca. Tentu, jika Anda bertanya, masyarakat yang mana, itu persoalan lain. Pertanyaan yang perlu diajukan, pada situasi dan kenyataan pasar di atas, apa yang ditawarkan oleh kedua novel tersebut?
Novel 99 Cahaya di Langit Eropa menceritakan perjalanan pasangan di Eropa, yang salah satu dari keduanya sedang menempuh studi doktoral. Narasi atau sastra perjalanan, pada mulanya, melekat pada kepentingan kolonial ketika penjelajah Eropa berlayar ke Timur. Itu sebabnya, narasi ini berkaitan erat dengan relasi Timur dan Barat. Dalam novel ini, kita bisa melihat bagaimana dalam konteks waktu yang lebih kemudian, perjalanan kontemporer yang dilakukan oleh orang Timur bersinggungan dengan identitas dan agama, dalam hal ini Islam di tengah situasi global. Dalam disertasinya, Akmal (2021) melihat bahwa novel ini memainkan strategi naratif untuk meletakkan Islam pada posisi pusat, sebuah wacana baru yang dibangun dengan nostalgia dan utopia, sedangkan Eropa adalah pinggiran dengan peran yang kecil. Sementara itu, dalam kedalaman narasi Laut Bercerita, kita bisa menerima, memahami, dan mengingat sejarah kekerasan yang mengiringi dinamika politik nasional dari Orde Baru menuju era Reformasi. Kita bisa melihat bahwa novel ini meletakkan situasi dan pergolakan politik orde besutan Soeharto sebagai frame yang membingkai bangunan naratifnya sehingga persoalan sosiologis-politis bisa dipersoalkan dari novel ini.
Idealis atau Menuruti Zaman dan Pasar?
Romi Arifin, pada paragraf kedua tulisannya, mengatakan, “Apakah sastra harus tetap idealis atau menjadi sastra yang mengikuti perkembangan zaman dan pasar”. Arifin mengakhiri kalimatnya ini dengan tanda titik meski sebetulnya, secara pragmatis, kalimat ini bertendensi mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini mengimplikasikan bahwa idealisme dan pasar adalah oposisi biner yang mustahil dekat dan menyatu, yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengarang pada saat yang bersamaan. Saya tidak mengetahui dan tidak ingin menerka-nerka apakah kehendak pengarang dua novel di atas ingin mendapatkan keuntungan pasar. Kalau pun benar, keinginan itu juga bukan sesuatu yang salah. Yang perlu ditekankan, sekali pun menulis atau mengarang di hadapan situasi zaman dan mekanisme pasar, kedua novel di atas, misalnya, mampu menawarkan nilai-nilai ideal tertentu sesuai dengan kepentingan ideologis dan politis dari pengarangnya masing-masing.
Jadi, dalam pandangan saya, argumentasi Arifin terlalu reduksionistik dan dikotomik terhadap dalam memandang idealisme dan pasar. Di antara kedua hal ini, pengarang pada dasarnya bisa dan memungkinkan untuk bernegosiasi dengan pasar. Pada saat yang sama, pengarang tetap menawarkan dan mempertahankan nilai-nilainya melalui strategi literer dalam karya sastra. Nilai-nilai apa yang tengah ditawarkan pun bermacam-macam karena karya sastra tidak terlepas dari berbagai kondisi-kondisi yang memengaruhi dan menentukan produksinya. Kata memengaruhi dan menentukan ini tidak berarti bahwa pengarang adalah subjek yang pasrah dan terikat pada kondisi pasar, misalnya. Sebaliknya, kondisi pasar itu memungkinkan dan memberdayakan mereka untuk bergerak dengan tetap mempertahankan idealismenya. Seperti yang dikemukakan Wolff (1993), tindakan kreatif (mengarang, misalnya) muncul karena kondisi struktural, tetapi manusia bukanlah robot sehingga kita perlu mempertimbangkan aspek biografis, eksistensial, dan motivasional.
Pandangan Wolff di atas, jika tertarik, diuraikan secara komprehensif dalam bukunya The Social Production of Art. Meskipun tidak secara khusus membahas karya sastra, konsep produksi seni yang dijelaskannya menawarkan ruang yang bisa kita masuki untuk melihat dialektika antara nilai-nilai ideal dan pasar dengan melihat dan meyakini bahwa pengarang memiliki kemampuan negosiasi, tidak justru berdiri di antara dua pilihan secara dikotomik. Sekali lagi, sebagai contoh, Leila S. Chudori katakanlah adalah penulis yang membutuhkan pangsa pasar atas novelnya. Namun, ia tentu punya aspek motivasi. Dalam banyak diskusi, ia sering mengatakan bahwa novel ini ditulis agar generasi muda tidak melupakan satu episode sejarah dalam pembentukan Indonesia yang penuh darah dan kekerasan. Contoh ini adalah contoh praktis dari konsep otonomi relatif dan politik kultural yang dikembangkan oleh Althusser (lihat Wolff, 1993). Meskipun dilingkupi oleh situasi ekonomi dan pasar, pengarang tetap mampu bersikap otonom, tidak sepenuhnya diam dan ditentukan, tetapi terberdayakan. Melalui karyanya, ia membangun narasi secara politis untuk kepentingan, tujuan, dan idealisme yang berbeda antara satu konteks ruang dan waktu dengan ruang dan waktu yang lain.
Tentang Ketidakpastian
Pada intinya, saya menolak argumentasi Romi Arifin yang dikotomik, yang melihat pengarang sebaliknya mengikuti pasar dan zaman sehingga implikasinya, idealisme bukan lagi hal yang penting. Namun, saya memahami bahwa argumentasinya ini dilandasi satu kegelisahan, yaitu ketidakpastian. Pada sebuah kalimat, ia mengatakan, “…banyak sastrawan harus adaptif dan menjadi masyarakat resiko yang tanpa kepastian dan selalu berusaha mencari kepastian dalam profesi sastrawan”. Menjadi pengarang atau sastrawan bukan hal yang mudah dan menulis karya sastra juga bukan pekerjaan enteng yang bisa dilakoni siapa pun. Harus digarisbawahi pula bahwa nasib tiap pengarang/sastrawan berbeda satu sama lain. Hal ini bisa kita lihat dengan konsep Bourdieu mengenai arena, agen, dan modal. Area merupakan bidang yang otonom secara parsial; di dalamnya aktor memperebutkan posisi dengan modal-modal yang dimilikinya (Richardus, 2020).
Pengarang karya sastra berada dalam satu arena yang sama, yaitu arena sastra (di Indonesia). Dalam arena tersebut terjadi kontestasi untuk merebut posisi sehingga tiap pengarang sebagai aktor dan agen secara aktif mengakumulasi dan mendayagunakan berbagai modal untuk merebut posisi tersebut. Ada berbagai modal, yaitu modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik (Richardus, 2020). Modal-modal tersebut merupakan perangkat kekuatan yang diaktifkan untuk bertarung dengan aktor-aktor lain sehingga dalam sebuah arena yang sama, mereka bisa mendapatkan posisi di hadapan masyarakat. Misalnya, dalam kasus Leila S. Chudori. Dia menempuh studi di Kanada, kemudian bekerja di Tempo, mengenal orang-orang yang pernah berurusan dengan militer Orde Baru. Hal ini adalah modal sosial dan modal simbolis yang membuatnya mendapatkan posisi untuk keluar sebagai pengarang Laut Bercerita dengan sambutan luas oleh masyarakat pada era Reformasi. Jadi, dengan modal yang tidak sama, posisi tiap pengarang akan berbeda dan demikian pula nasibnya.
Kembali pada soal tanpa kepastian yang dimaksudkan oleh Romi Arifin, tulisannya secara tidak langsung mengatakan bahwa ketidakpastian itu muncul di tengah situasi yang serba ditentukan oleh pasar. Pada akhir tulisannya, ia mengutip tulisan Sutopo dan Meiji tentang pemuda dalam perspektif transisi. Ada masalah di sini. Pertama, tidak semua pengarang adalah anak muda meskipun sekarang memang banyak muncul pengarang-pengarang muda (definisi pemuda pun perlu diperjelas). Saya juga tidak menemukan data siapa pengarang yang benar-benar menggantungkan hidupnya pada karya sastra dan menulis karya sastra; juga siapa pengarang yang menjadikan aktivitas ini sebagai kerja lain di luar kerja utama. Ketiga, apa yang dimaksud dengan ketidakpastian? Kata ketidakpastian ini lekat pada keadaan krisis. Saya pikir, dalam situasi pasar, bukan kepastian atau ketidakpastian, melainkan siapa yang sanggup dan tidak sanggup untuk bertahan.
Jika Romi Arifin melihat zaman pasar sebagai hambatan bagi pengarang, saya pikir dia terlalu mensimplifikasi fakta. Ada pengarang yang karyanya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan ia mendapatkan berbagai penghargaan. Ada pengarang yang menyuguhkan tema-tema seksualitas secara vulgar sehingga karya-karyanya mendapatkan penerimaan yang luar biasa. Keadaan-keadaan ini begitu kompleks dan sering kali, posisi pengarang tidak lepas dari konteks politik. Untuk mendapatkan posisi, saling berkontestasi dengan berbagai modal dalam arena sastra adalah hal yang menurut saya biasa saja. Untuk mendapatkan predikat sebagai sastrawan, ada berbagai modal yang harus dikerahkan untuk kemudian bisa mencapai posisi ekonomi tertentu. Predikat itu juga bukan sesuatu yang gampang disematkan begitu saja. Pasti atau tidaknya mereka untuk diterima oleh publik, pasti dan tidaknya karya(-karya) mereka untuk disambut masyarakat sastra, ditentukan oleh seberapa kuat modal yang mereka miliki, akumulasi, dan gunakan. Modal-modal itulah yang menentukan apakah dengan karyanya, ia sanggup bertahan atau justru kalah di arena kesusastraan.
Untuk Romi Arifin
Tulisan Arifin, dengan sejumlah kritik yang saya utarakan, memungkinkan untuk dibahas lebih dalam. Pada zaman pasar, posisi pengarang/sastrawan dan karya sastra, baik dalam konteks Indonesia maupun global, perlu ditinjau pada lain kesempatan dengan porsi yang lebih intensif dan ekstensif. Paling tidak dalam konteks tulisan ini, saya perlu menekankan bahwa Anda terlalu simplistis untuk melihat relasi pasar dan idealisme dalam karya sastra secara dikotomik. Produksi karya sastra sebagai karya seni bukanlah sesuatu yang tunggal, tetapi kompleks dengan berbagai relasi sosial, pasar, politik, dan budaya yang melingkupinya. Dikotomi yang Anda bangun justru memutus berbagai relasi yang memungkinkan untuk kita persoalkan lebih lanjut. Menurut saya, bukan soal sastra komoditas, melainkan bahwa pengarang secara relatif mampu melampaui komoditas itu, yaitu dengan mempertahankan nilai-nilai politis-ideologisnya masing-masing meskipun berhadapan pada situasi pasar. Terima kasih kepada Romi Arifin yang telah mengawali diskusi ini lewat tulisannya.
Daftar Pustaka
Akmal, R. 2021. “The Self, the Other, and the World: Narratological construction of subjectivity in Indonesian travel literature on Europe after Reformasi”. Disertasi. Hamburg: Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Hamburg.
Arifin, R. 2023. “Sastra Komoditas”. Diakses dari https://lpmperspektif.com/2023/10/15/sastra-komoditas/.
Chudori, L.S. 2017. Laut Bercerita. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
DetikHot. 2014, November 1. “Novel 99 Cahaya di Langit Eropa Raih Penghargaan ‘Book Of The Year’”. DetikHot. Diakses dari https://hot.detik.com/art/d-2736369/novel-99-cahaya-di-langit-eropa-raih-penghargaan-book-of-the-year.
Hayati, I. 2022, Juli 13. “Novel Leila Chudori, Laut Bercerita Sudah Dicetak 48 Kali dalam 5 Tahun, Penerbit: Luar Biasa”. Tempo.co. Diakses dari https://seleb.tempo.co/read/1611398/novel-leila-chudori-laut-bercerita-sudah-dicetak-48-kali-dalam-5-tahun-penerbit-luar-biasa.
Rais, H.S. & Almahendra, R. 2013. 99 Cahaya di Langit Eropa: Perjalanan Menapak Jejak Islam di Eropa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Richardus, W.N.C. 2020. “Ruang Sosial Bourdieusian”. Dalam W. Udasmoro (ed.), Gerak Kuasa: Politik Wacana, Identitas, dan Ruang/Waktu dalam Bingkai Kajian Budaya dan Media (hlm. 293—316). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Windayanto, R.N.A. 2022. “Transformasi Cerita dalam Hikayat Wayang Pandu”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
Wolff, J. 1993. The Social Production of Art. Second edition. Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 2XS dan London: The Macmillan Press Ltd.