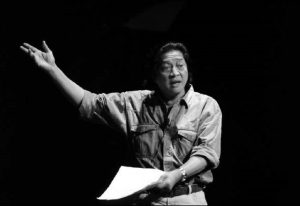Luas pertanian sorgum di Nusa Tenggara Timur mencapai 2.840 hektare, tersebar di 14 kabupaten. Panen di Dusun Likotuden mampu menghasilkan Rp. 6 juta per hektare.
Flores Timur, PERSPEKTIF – Agata Hore Kola mengambil sebilah parangnya—kala mentari sedang menguncup—untuk bersiap pergi ke ladang. Sehelai kain digantung di pundak, berjaga-jaga dari terik yang bakal menyemburat siang nanti. Sama seperti kebanyakan warga dusun lainnya, wanita lima puluh tahun itu menggantungkan hidup sebagai seorang petani sorgum.
Bersama dengan suaminya, Siprianus Waitu Hera, Agata menapaki jalan bersemen menuju gapura kampungnya. Di sana terlihat hamparan ladang mereka yang berimpit dengan kebun milik masyarakat Dusun Likotuden, Desa Kawalelo, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dusun Likotuden sudah tak asing lagi sebagai wilayah penghasil sorgum terbaik di provinsi tersebut. Mereka bahkan memiliki beberapa varietas unggulan. Pertanian sorgum di Likotuden menjadi satu dari belasan area pengembangan di NTT. Dinas Pertanian Provinsi NTT menyebut bahwa mereka memiliki 2.840 hektare lahan yang tersebar di 14 kabupaten, termasuk di antaranya Kabupaten Flores Timur.
Ladang milik Agata dan suaminya menjadi satu di antara daerah pengembangan sorgum. Lokasinya berada di Tanjung Lopez—sebuah wilayah karst Dusun Likotuden—di tepi Laut Sawu yang curam. Kebun seluas 1,75 hektare tersebut tepat menghadap birunya laut, bagian dari Taman Nasional Perairan Laut Sawu. “Di sini masih berlangsung musim tanam padi, jagung, dan tumpang sari dengan sorgum,” kata Agata ketika ditemui pada Senin (19/02).
Menurut dia, hampir seluruh pola pertanian di Likotuden berbentuk ladang. Ini karena masyarakat hidup di daerah yang memiliki curah hujan rendah dan tanah berbatu. Ibu empat anak itu lalu menunjukkan bagaimana sorgum miliknya mulai bertunas, tengah tumbuh subur di antara batuan sedimen. .
Di hari itu, ia harus menyiangi rerumputan yang mulai tumbuh lebat. Adapun suaminya sibuk memegangi sebuah tongkat kayu di tangan kiri. Pria berusia enam puluh sembilan tahun itu menghujamkan ujung tongkat ke bumi untuk membentuk lubang. Menyusul tangan kanannya gesit menuangkan butiran biji sorgum. Mereka menyebut itu sebagai proses penyulaman untuk menggantikan bibit sebelumnya yang gagal bertunas.
Keluarga Agata memilih fokus menanam sorgum karena padi dan jagung yang ditanam pada November tahun lalu gagal panen. Musababnya adalah kemarau panjang akibat fenomena alam El Nino. Perubahan cuaca yang drastis mengakibatkan padi dan jagung sulit tumbuh.
“Padi yang kami tanam pertama itu mati. Mau tanam lagi ternyata sudah memasuki bulan kedua musim tanam, sehingga harapan untuk tumbuh subur sudah menipis karena hujan akan habis,” ujar dia. Sampai tiga bulan kemudian pun ukurannya masih kerdil dan menjadi niscaya keluarga Agata gagal panen.
Agata mafhum bila menanam jagung dan padi di tanah mereka bakal sangat rentan untuk gagal panen. Tersebab tanaman tidak tahan dengan kondisi krisis iklim yang diakibatkan cuaca tidak menentu. “Seperti ini, padi dan jagung mati seperti dimakan matahari saja,” ujar Agata terkekeh meskipun raut wajahnya tampak getir.
Rugi, memang! Agata dan suaminya harus memutar otak untuk tidak berserah. Mereka lalu mengganti padi dan jagung yang telah tumbuh dengan sorgum yang dinilai lebih tahan terhadap curah hujan yang sedikit. Klaimnya, tanaman ini cocok dengan kondisi iklim di Flores Timur yang gersang.
Benih Sorgum yang Terlupakan
Hadirnya sorgum sebagai komoditas pertanian di Dusun Likotuden bukan barang baru bagi masyarakat. Tanaman ini bahkan sudah menjadi bagian dari warisan leluhur di Nusa Tenggara Timur (NTT). Karakteristiknya khas, yakni mampu bertahan dan tumbuh subur di tengah minimnya curah hujan dan tingginya suhu di bumi berjuluk Nusa Terindah Toleransi tersebut.
Pertanian sorgum sempat ditinggalkan di masa pemerintahan Orde Baru. Ketika pemerintah menggencarkan program ekonomi hijau berupa kampanye swasembada beras sebagai bagian dari program ketahanan nasional. Gerakan ini menyebabkan pupusnya pengetahuan masyarakat terhadap diversifikasi pangan, terutama pada tanaman sorgum.
“Dulu kami tanam padi dan jagung buat makan-minum saja susah. Sekarang kalau padi dan jagung gagal panen, kami masih ada sorgum,” ucap Agata. Kondisi kian parah ketika curah hujan semakin sedikit dari tahun ke tahun. Tidak heran bila jumlah produksi padi dan jagung semakin sedikit dan sangat rentan gagal panen.
Pernyataan Agata ini selaras dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Timur. Pada 2020, jumlah produksi padi di Kabupaten Flores Timur sebesar 11.165 ton. Namun merosot menjadi 8.089 ton di tahun berikutnya. Penurunan produksi terus terjadi pada 2022 dengan hanya 7.517 ton.
Begitu juga dengan produksi jagung di Flores Timur. Pada 2020 produksinya mencapai 18.631 ton. Sempat meningkat menjadi 20.118 ton pada 2021. Namun kembali turun setahun berikutnya yakni 18.426 ton pada 2022. “Kalau gagal panen padi dan jagung itu suami saya pergi tembak ikan di laut, saya jual,” kata dia.
Padahal, tanaman sorgum sebetulnya sudah menjadi bagian dari cerita rakyat dengan legenda Tonu Wujo. Ketika seorang perempuan yang dikisahkan mengorbankan dirinya agar semua anggota keluarganya tidak mati kelaparan saat paceklik melanda. Perempuan bernama Tonu Wujo itu berpesan bahwa semua tanaman pangan akan tumbuh setelah dia mati.
Tumbuh tanaman pangan dari tubuh Tonu Wujo. Darahnya menjadi padi, tulang belulangnya tumbuh sorgum, dan ususnya menjelma jewawut atau biji serealia. Bahkan rambutnya menjelma jagung. Kemasyhuran cerita sorgum ini ternyata berhasil mengatasi krisis pangan di Flores Timur dampak perubahan iklim.
Institut Pertanian Bogor bahkan menyebut biji-bijian sorgum mengandung karbohidrat setara dengan protein pada padi. Juga memiliki vitamin B dan zat besi yang tinggi. Bahkan sorgum memiliki kandungan pati lebih rendah ketimbang beras sehingga tidak cepat menaikkan gula darah.
Memperbaiki Kesejahteraan dengan Biji Solor
Agata Hore Kola mengingat kunjungan Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (Yaspensel)—perwakilan Keuskupan Agung Larantuka—ke kampungnya pada 2014 silam. Tujuan mereka mengampanyekan bibit sorgum sebagai upaya diversifikasi pangan di Pulau Flores. Agata saat itu merasa asing mendengar tanaman dengan nama latin sorghum bicolor tersebut.
Kelak mereka mengetahui bahwa sorgum di Flores Timur dikenal dengan sebutan jagung solor. Hanya saja sudah sangat lama tidak digunakan sebagai bagian dari pilihan pangan alternatif. Sehingga pada mula dikenalkan oleh Yaspensel, hanya 25 keluarga petani yang bersedia menanam tumbuhan ini.
Petani yang lain masih ragu dengan jenis tanaman garai itu. Apalagi nama pangan tersebut tidak pernah terdengar di pasar lokal. Tak heran muncul kekhawatiran Agata ketika menghitung untung dan rugi bila beralih ke pertanian sorgum. Hal ini memicu pembelahan di masyarakat bahkan sampai di dapur Agata.
Agata dan suaminya sempat tak sependapat untuk menanam biji sorgum di ladang mereka. Agata bersikeras untuk membuka lahan dan menanam, sedangkan suaminya tetap enggan. “Sorgum itu kan sebuah makanan. Kita makan baru bisa hidup, jadi tidak mungkin orang mau kasih tunjuk kita yang tidak baik. Karena saya pikir seperti itu makanya tetap kepala batu. Suami tidak mau, tapi saya tetap buka lahan,” ujar Agata.
Agar nekat membuka lahan sorgum seluas 625 meter. Hasil panen pertama sangat memuaskan. Sang suami yang awalnya menolak menanam kemudian ikut membantu dan mereka menambah luas lahan menjadi 1,75 hektare. Dengan lahan seluas itu, mereka dapat memproduksi 2 ton sorgum untuk tiap kali panen.
Ketika dijual, keuntungan yang mereka peroleh mencapai Rp. 12 juta. “Itu untuk sekali panen. Enaknya sorgum kita tanam sekali, panennya bisa tiga kali kalau hujan bagus. Kalau hujannya kurang minimal dua kali dalam setahun,” ucap dia.
Ia lalu membandingkan dengan keuntungan menanam padi dan jagung. Dalam sekali panen mereka hanya menghasilkan sebesar 720 kilogram. Jika dijual, keuntungan yang mereka peroleh hanya Rp. 7-8 juta saja. Itu pun tanaman padi dan jagung hanya bisa ditanam sekali dalam satu tahun.
Kisah sukses keluarga Agata lantas ditiru oleh banyak keluarga di Dusun Likotuden. Berjalannya waktu, mayoritas penduduk kampung tersebut menikmati hasil panen komoditas sorgum. Ini akhirnya mendorong mereka membentuk sebuah usaha bersama (UB) pada 2016. Kemudian pada 2020, kelompok tani ini sudah berbadan hukum dan dinamai Koperasi Produksi Sorgum Likotuden.
Pengurus Koperasi Produksi Sorgum Likotuden Gregorius Soba Tobin mengatakan saat ini anggota mereka sudah mencapai 45 orang. Masing-masing anggota diwajibkan memiliki lahan sorgum minimal satu hektare. “Ketika panen, koperasi bisa menampung lebih dari 40 ton sorgum milik anggota,” tuturnya.
Gregorius mengatakan bahwa dengan menanam sorgum, anggota koperasi bisa berpenghasilan lebih dari Rp. 9 juta untuk tiap kali panen. Hal ini membuat masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya. “Makan dan minum bisa terpenuhi karena kami menerapkan pembagian 60 persen untuk dijual dan 40 persen untuk konsumsi dalam rumah tangga,” jelasnya.
Dengan penghasilan seperti itu, banyak kebutuhan masyarakat yang menjadi terpenuhi berkat menanam sorgum. Kata Gregorius, hal tersebut tidak mungkin mereka dapat jika hanya menanam padi dan jagung saja. “Contoh dampaknya itu, dulu banyak masyarakat yang cuma lulus sekolah menengah pertama (SMP) saja, sekarang sudah banyak yang bisa lanjut sekolah menengah atas (SMA), bahkan sampai kuliah.”
Perbaikan pendidikan ini juga dinikmati tiga dari empat anak Agata yang kini sudah lulus SMA. Bahkan Agata tengah mempersiapkan anak bungsunya untuk bisa kuliah Pendidikan Bahasa Inggris di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Berkah biji jagung solor bahkan bisa membuat Agata dan keluarga memperbaiki rumah. Cerita dia, dulu keluarganya tidur di tikar yang dibentangkan di lantai. Kini sudah terasa lebih empuk karena berganti kasur pegas atau spring bed. Jendela rumah yang semula dari bambu kini berganti kaca. “Perbedaan-perbedaan ini buat saya merenung, kenapa tidak dari dulu tanam sorgum. Sejak dulu kami makan-minum saja susah, bagaimana kebutuhan lain mau cukup,” ujarnya.
Menabur Kejayaan di Pulau Flores dan Lembata
Pengalaman sukses di Dusun Likotuden membuat Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (Yaspensel) semakin giat untuk terus menyebarkan semangat kembali ke pangan lokal. Mengampanyekan sorgum sebagai bagian dari diversifikasi pangan. “Sehingga perhatian besar untuk wilayah Pulau Flores dan Lembata untuk mengangkat kembali pangan lokal guna mengatasi krisis iklim,” kata Direktur Yaspensel Benyamin Daud Apelabi.
Usaha untuk melestarikan pangan lokal tak hanya dilakukan Yaspensel sendiri. Mereka turut menginisiasi gerakan sosial bersama organisasi masyarakat sipil melalui Koalisi Pangan Baik. Tujuannya untuk mengatasi krisis iklim di pulau itu. Kelompok ini terdiri dari Yayasan Hayati Indonesia (Kehati), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Yayasan Ayu Tani Mandiri, Ayo Indonesia, dan Yaspensel.
Dalam usahanya, Koalisi Pangan Baik menggandeng anak muda yang ada di desa-desa binaan. Mensosialisasikan isu krisis iklim di wilayahnya masing-masing. Selain itu, mereka juga menggerakan masyarakat untuk kembali memproduksi dan mengkonsumsi pangan lokal sebagai solusi krisis pangan. Anak-anak muda ini mereka namakan sebagai Local Champion (LC). Saat ini sudah ada LC Koalisi Pangan BAIK di 13 Desa yang tersebar di Pulau Flores dan Lembata.
Di wilayah Kabupaten Flores Timur terdapat empat desa binaan yaitu Desa Kawalelo, Aransina, Hokeng Jaya, dan Desa Hewa. “Program kami fokus untuk mendorong kelompok rentan bersuara terkait perubahan iklim. Kami juga menanam kembali beberapa jenis pangan lokal antara lain; padi lokal, jagung lokal, sorgum, jali-jali, jewawut, umbi-umbian, sayuran, dan lain-lain,” ujar I’im seorang LC Koalisi Pangan Baik.
Selain itu, Koalisi Pangan Baik juga melakukan pengarsipan data 17 padi lokal, 5 jenis jagung lokal, dan beberapa jenis umbi-umbian serta kacang-kacangan. Tanaman-tanaman tersebut telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat setempat sebagai pangan pokok. Dengan ini, masyarakat Pulau Flores dan Lembata sudah mempunyai budaya diversifikasi pangan sejak dahulu.
Dalih Penyeragaman Beras untuk Swasembada Pangan
Usaha yang dilakukan Koalisi Pangan Baik untuk menggalakkan kembali pangan lokal masih menemui kendala. Salah satunya karena masifnya hegemoni beras sebagai pangan pokok masyarakat Indonesia.
Direktur Yaspensel, Benyamin Daud Apelabi bercerita, upaya penyeragaman konsumsi terjadi pada zaman pemerintahan Soeharto. Semua penduduk di kala itu diwajibkan menanam padi. Pada masa-masa paceklik itu, pangan-pangan lokal yang sudah dikonsumsi masyarakat sejak ribuan tahun sebelumnya mulai ditinggalkan.
Akibatnya beras padi menjadi satu-satunya pangan pokok dan menyebabkan ketergantungan masyarakat. “Maka pangan-pangan lokal kita ditinggalkan lalu pada perjalanan itu beras dari padi lebih menonjol. Jadi masyarakat itu lebih memilih padi daripada yang lain. Sampai akhirnya kami di Flores sudah terpengaruh dengan kebijakan berasisasi,” ujarnya.
Ucapan Benyamin linier dengan catatan BPS yang menunjukkan produksi beras di NTT mencapai 442.842 ton pada 2022. Sedangkan tingkat konsumsi beras hampir satu juta ton per tahun. Artinya provinsi ini mengalami defisit beras dan harus menggantungkan hidup dari daerah penghasil beras. Tak mengherankan harga beras di Kabupaten Flores Timur kini mencapai Rp 16.000 per kilogram.
Pelaksana tugas Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTT Yuvensius Stevanus Nonga mengatakan penyeragaman konsumsi ini juga berpengaruh terhadap kebijakan pertanian yang dikeluarkan pemerintah daerah. Menurut dia, pemerintah selalu hadir dengan ide-ide kebijakan monokultur yang kian menggerus adaptasi perubahan iklim yang sebenarnya sudah diterapkan masyarakat.
“Selagi pemerintah memikirkan masa depan pertanian itu sangat tergantung pada kebijakan monokultur seperti food estate, maka saat itu pemerintah membangun ketergantungan yang berkepanjangan bagi masyarakat,” ucap dia.
Menurut Yuven—jika ingin memandang masa depan pertanian di NTT—pemerintah mestinya melibatkan para petani. Tujuannya menentukan kebijakan pertanian yang cocok di dataran kepulauan yang gersang tersebut. Hal tersebut akan menguatkan potensi pangan lokal. “Di NTT ada sorgum, jagung lokal, dan umbi-umbian. Setiap daerah di NTT punya banyak potensi pangan-pangan lokal,” tuturnya.
Pegiat Pangan NTT Maria Loretha ikut menyerukan agar pola pertanian dan konsumsi pangan harus kembali pada kearifan lokal. Bukan justru seperti
kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2015. “Di dalamnya justru mengatur percepatan swasembada padi, jagung, dan kedelai, yang justru menghambat pemerintah daerah untuk mengembangkan varietas lokal yang sesuai karakteristik NTT,” kata Maria Loretha.
Loretha menambahkan bahwa pemerintah juga harus melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil atau komunitas yang telah mempunyai rekam jejak baik dalam mengurus pangan lokal. Terutama agar kebijakan pangan tidak dibuat sentralistik dengan komoditas tertentu yang sebenarnya tidak dikonsumsi masyarakat NTT. “Padahal orang Flores Timur dan Lembata itu, kalau tidak ada beras juga biasa makan pisang, ubi, dan jagung,” tuturnya.
Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Apolinardius Yosep Lia Demor tak menepis bahwa pemerintah masih konsentrasi pertanian komoditas padi dan jagung. Namun kini produksinya mengalami penurunan akibat kekeringan berkepanjangan. “Ini mengakibatkan indeks penanaman (IP) di daerah ini hanya sebanyak dua kali saja setahun,” kata Demor ketika dikonfirmasi.
Beberapa intervensi sudah dilakukan pemerintah daerah dengan menyiapkan dari persediaan benih padi. Termasuk di dalamnya fasilitas produksi dan hingga masa panen datang. Misalnya dengan pembuatan sumur bor yang memakan anggaran sebesar Rp. 300 juta untuk tiap unit. Pemerintah setempat juga menyiapkan aplikasi digital pembaca cuaca bagi kelompok tani.
Demor turut menjelaskan ihwal program Tanam Jagung Panen Sapi (TPJS) yang dinilai gagal. Klaim dia, tersebab rendahnya kemauan petani. Padahal pemerintah Flores Timur sudah mengalokasikan bantuan Rp 10 juta per hektare bagi masyarakat yang menanam jagung. Hematnya, pemerintah hanya mampu mengembangkan 25 hektare dari 3.000 hektare target penanaman kebun jagung.
Kini Pemerintah Kabupaten Flores Timur lebih banyak ikut mensosialisasikan diversifikasi tanaman pangan lokal. Mereka menyadari pemerintah harus menekan ketergantungan masyarakat terhadap beras. “Kita harapkan potensi-potensi pangan lokal kita yang memang cocok dengan iklim sekitar,” ucap Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Maria Fernandez.
Kata Maria, pemerintah daerah sudah memiliki Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal di Kabupaten Flores Timur. Kebijakan ini kemudian melahirkan jargon: “Nona Sari Setia; No Nasi Satu Hari Sehat Bagia Aman”. Program ini menyarankan agar semua perangkat daerah dan masyarakat Flores Timur puasa nasi minimal satu hari dalam tiap pekan.
Maria menjelaskan bahwa pemerintah telah mengupayakan tanaman lokal seperti sorgum bukan hanya sebagai pangan alternatif, tapi menjadi pangan pokok daerah. Pemerintah sudah membantu sampai kendaraan atau fasilitas pengolahan sorgum. “Kalau ada potensi pertanian sorgum di desa-desa, kita akan bantu dari benih sampai alat-alat pasca-produksi. Kemasan juga kita siapkan,” ujar Maria. (gra/cns)
Laporan ini merupakan kerjasama LPM Perspektif dan The Conversation Indonesia dalam Environmental Journalist Bootcamp 2024.