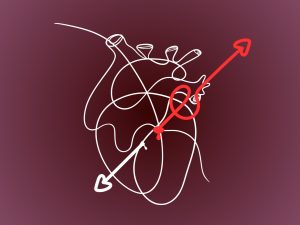Menurut Pasal 28C Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, pendidikan adalah hak asasi manusia. Hakikatnya sebagai hak asasi berarti bahwa pendidikan harus bisa digapai dengan mudah oleh berbagai kalangan, termasuk kaum disabilitas. Melalui Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003, menunjukkan bahwa negara menjamin sepenuhnya pendidikan bermutu bagi anak berkebutuhan khusus. Namun, yang seringkali terjadi adalah pendidikan bagi kaum disabilitas diwadahi secara khusus dengan model pendidikan segregatif melalui Sekolah Luar Biasa (SLB). Dewasa ini, muncul upaya dari pemerintah untuk menggeser model pendidikan tersebut menjadi integratif dengan memasifkan inklusivitas pendidikan. Hal ini sesuai dengan penjelasan oleh Sapon-Shavin (seperti dikutip oleh Andini & Rahayu, 2020) bahwa pendidikan inklusif adalah jenis pendidikan yang memastikan semua anak yang memiliki kebutuhan khusus mendapatkan layanan di sekolah terdekat dan berada di kelas reguler bersama teman-teman sebayanya secara holistik.
Sudah ada upaya dari negara mengenai pendidikan inklusif. Namun pada kenyataannya, pada implementasinya seringkali ditemukan ketidaksesuaian. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (2020), ada penurunan yang cukup besar dalam tingkat partisipasi pendidikan masyarakat disabilitas seiring dengan naiknya tingkat pendidikan, terutama bila dibandingkan dengan masyarakat non-disabilitas. Data dari Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan pada masyarakat disabilitas mencapai 15%, yang jauh lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 9.2%. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) pada tahun 2020 telah mengungkapkan bahwa terdapat korelasi kuat antara disabilitasl, akses yang terbatas, dan kemiskinan. Dengan kata lain, proses pembangunan yang ada saat ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat disabilitas. Ini juga menunjukkan bahwa topik pembangunan belum secara efektif melibatkan masyarakat difabel dalam perencanaan, proses pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
Universitas Brawijaya (UB), sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin pendidikan yang inklusif. Menurut data dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Universitas Brawijaya pada tahun 2022 menempati posisi tiga besar universitas dengan jumlah mahasiswa penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Disabilitas tahun 2022 tertinggi di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga melaporkan bahwa UB pada tahun 2022 memiliki jumlah mahasiswa disabilitas terbesar di Jawa Timur, sebanyak 112 mahasiswa. Walaupun begitu, penilaian kampus paling inklusif seharusnya tidak hanya didasarkan dari jumlah penerimaan. Namun, penilaian tentang kesiapan infrastruktur, tenaga pendidik, dan lingkungan pergaulan seharusnya diperhatikan agar mahasiswa disabilitas dapat menjalani dinamika belajarnya secara optimal.
Di lingkungan internal UB, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) telah menunjukkan upaya inklusivitas dibandingkan fakultas lainnya di Universitas Brawijaya. Ada beberapa fasilitas penunjang yang dibangun untuk mendukung proses belajar mahasiswa disabilitas seperti toilet khusus difabel, tombol tambahan di lift Gedung C, braille lift buttons di setiap lift, dan juga adanya ramp untuk kursi roda. Selain itu, diberikan pula kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam organisasi kemahasiswaan, asisten praktikum, dan kepanitiaan. Mereka juga mendapatkan pendamping untuk mempermudah proses belajar mereka.
Meskipun begitu, pembentukan ruang inklusif melalui berbagai aspek perlu dilaksanakan secara proaktif daripada reaktif. Reaksi tersebut adalah hal yang bagus karena ditanggapi dengan responsif, tetapi untuk menciptakan ekosistem pendidikan inklusif yang maksimal, akan lebih baik apabila pihak kampus proaktif menyiapkan fasilitas disabilitas meskipun belum ada mahasiswa disabilitas yang berkukuah. Dengan begitu, mahasiswa disabilitas yang akan masuk ke kampus, sudah bisa menjalankan pendidikannya dengan optimal.
Selain faktor fasilitas, Rohaeti (2009) menyampaikan bahwa hubungan sesama mahasiswa merupakan salah satu faktor pendorong kesetaraan disabilitas di perguruan tinggi. Seringkali hal ini tidak disadari oleh sesama mahasiswa dan menimbulkan masalah. Pada beberapa kesempatan, kami menemukan bahwa mahasiswa disabilitas menghadiri perkuliahan sendirian meskipun pada SOP mahasiswa disabilitas memiliki pendampingnya masing-masing saat menjalani kegiatan perkuliahan. Pada beberapa kasus yang ditemukan, tidak adanya pendamping disebabkan karena kurangnya tenaga bantu pada Pusat Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya. Kebanyakan tenaga pendamping adalah mahasiswa yang notabene memiliki keterbatasan atau kesibukan yang mungkin bertabrakan dengan jadwal mahasiswa disabilitas. Sehingga, penting untuk disediakan tenaga tambahan yang non-mahasiswa agar memiliki waktu yang fokus untuk mendampingi mahasiswa disaibiltas.
Memandang fenomena tersebut, sebagai rekan mahasiswa seharusnya kita lebih peka untuk membantu mereka. Akan tetapi, kita perlu paham cara dan “taraf” kita dalam memberikan kepekaan lewat tindakan-tindakan konkret untuk membantu mereka. Jangan sampai kita bersikap hanya berdasarkan rasa kasihan. Berdasarkan berbagai interaksi / perbincangan penulis dengan teman-teman disabilitas terdekat, mereka menyampaikan bahwa dirinya seringkali merasa ‘dispesialkan’ karena adanya rasa kasihan dari mahasiswa lain. Padahal, ketika berinteraksi sesama mahasiswa, mereka lebih ingin dipandang sama dengan yang lain. Tidak perlu perasaan kasihan, sungkan, atau bahkan iba, karena memberikan perlakuan yang spesial justru membuat mereka tidak nyaman. Perasaan untuk memandang spesial mahasiswa disabilitas secara tidak langsung memberikan persepsi bawah mahasiswa non-disabilitas dilihat sebagai penolong atau orang yang lebih mampu dibanding mahasiswa difabel.
Munculnya perlakuan yang spesial tersebut, biasa disebut dengan savior complex atau white knight syndrome. Seringkali, terdapat orang datang memberikan bantuan yang sebenarnya tidak dibutuhkan. ‘Penyelamat’ ini seakan yakin bahwa dia adalah orang yang lebih baik dari orang lain, dan merasa harus menyelamatkan orang yang dikasihaninya. Padahal, dalam dunia nyata, orang tidak butuh diselamatkan, mereka butuh solusi sistemik untuk mengatasi ketidaksetaraan. Kasus yang mungkin sering terjadi adalah adanya rasa iba yang tidak perlu. Iba yang tidak perlu sering kita jumpai atau kita lakukan terhadap teman-teman disabilitas saat bercanda dengan mereka. Contoh, ketika ada mahasiswa A yang bercanda dengan mengejek mahasiswa B (non-disabilitas) seperti jamet karena mewarnai rambutnya, semua temannya tertawa. Tetapi, ketika mahasiswa A bercanda dengan mengejek mahasiswa C (disabilitas) seperti jamet karena mewarnai rambutnya, semua temannya seakan-akan tidak nyaman dan menasihati mahasiswa A agar tidak mengejek atau membuat candaan kepada mahasiswa disabilitas. Padahal, mahasiswa difabel juga ingin dianggap setara. Mereka juga ingin bersenda gurau dan dianggap setara seperti teman non-disabilitas lain. Hal tersebut mungkin sering kita lakukan tanpa kita sadari. Kita berpikir kita peduli dengan teman disabilitas, namun disisi lain kita tidak melihat mereka setara dan justru memberikan perlakuan berbeda secara tidak sadar.
Hal tersebut selaras seperti yang dijelaskan jurnalis Amerika Serikat, Jordan Flaherty dalam bukunya “No More Heroes: Grassroots Challenges to the Savior Mentality”. Sebagai contoh, Flaherty menyampaikan bahwa donasi atau kegiatan volunteering kepada mereka yang kurang beruntung mengandung konsekuensi yang mematikan. Donasi dan volunteering hanya membantu kelompok tertentu pada waktu yang kecil, padahal kelompok tersebut perlu solusi sistemik yang bisa mengembangkan mereka secara berkelanjutan. Maka dari itu, pembenahan sistem, pelatihan keterampilan, dan hal lain yang sifatnya community development akan lebih baik daripada kegiatan yang sifatnya community service. Pemahaman dan praktik mengenai inklusifitas perlu dikaji dan ditingkatkan lebih baik lagi guna memahami akar penyebab serta hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang merupakan instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas harus dilakukan dan harus diratifikasi oleh Negara kita agar menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Menyambung dengan hal tersebut, solusi dan tindakan yang dilakukan untuk menuntaskan permasalahan disabilitas kebanyakan menggunakan cara-cara sepihak. Solusi yang diberikan hanya berdasarkan pandangan bahwa kaum disabilitas merupakan kaum yang membutuhkan bantuan dan lebih ‘lemah’. Perlu adanya penyelesaian masalah secara partisipatoris, yakni melibatkan mereka dalam penyelesaian masalah inklusivitas ini. Jadi, solusi atau penyelesaian yang dihasilkan melalui proses penyusunan bersama dengan berbagai pihak terutama kaum disabilitas. Pihak terkait disini seperti pemerintah dan kampus bukan hanya sebagai penyedia fasilitas dan perumus kebijakan, namun juga sebagai pendengar serta menjadi mitra kaum difabel dalam menyediakan layanan inklusif pada dunia pendidikan.
Permasalahan inklusivitas bukanlah tentang siapa yang menjadi pahlawan dan siapa yang akan ditolong. Permasalahan inklusivitas di kampus terlebih di setiap fakultas Merupakan permasalahan bersama antara pihak universitas, mahasiswa disabilitas dan mahasiswa non disabilitas. Cara pandang dalam melihat permasalahan tersebut harus mulai diganti oleh setiap civitas akademika yang ada pada kampus. Permasalahan inklusivitas yang merupakan masalah bersama seharusnya dalam penyelesaiannya disusun dan dilakukan bersama oleh setiap pihak dengan mengesampingkan posisi tertentu serta mengutamakan kesetaraan. Memberikan perlakuan khusus ketika berinteraksi, ataupun memberikan rasa iba yang tidak perlu kepada mereka tidak akan menyelesaikan permasalahan mereka. Penting bagi kita untuk memandang mereka secara personal sebagai individu yang setara dengan kita, tanpa melupakan bahwa kita harus berjalan berdampingan dengan mereka untuk membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif lagi di Indonesia. Akhir kata, bukan yang ‘normal’ menjadi penolong, tetapi sudah normalkah menganggap diri sebagai penolong.