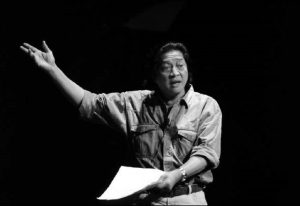Negara adalah mesin pencerita yang lihai. Ia mengarang narasi untuk menyulam ketakutan kolektif, membaptisnya sebagai “darurat” demi membenarkan instrumen represi yang dipanggul aparat.
Sejarah kekerasan negara bukanlah serangkaian insiden, melainkan struktur yang mapan, sistematis, dan dilembagakan. Di dalamnya, aparat keamanan berfungsi sebagai palang pintu kekuasaan yang menentukan siapa yang boleh berbicara dan siapa yang harus dibungkam. Pada titik ini, sulit memisahkan aparat negara dari kekerasan—keduanya terjalin dalam jaringan yang tak terpisahkan.
Walter Benjamin menggambarkan fenomena ini sebagai bagian dari kekerasan “murni” yang ada dalam hukum. Dalam karya esensialnya, Critique of Violence (Zur Kritik der Gewalt), Benjamin menunjukkan bahwa hukum tidak dapat ditegakkan tanpa kekerasan, dan kekerasan itu sendiri merupakan fondasi dari hukum negara. Kekerasan negara yang dilakukan oleh polisi dan tentara, dengan demikian, bukanlah pengecualian, ia adalah bagian integral dari bagaimana hukum dan negara itu sendiri bekerja. Dengan kata lain, negara berbicara pada rakyatnya dengan bahasa kekerasan, dan polisi serta tentara adalah juru bicaranya.
Akhirnya polisi dan tentara hadir sebagai instrumen; ia adalah manifestasi dari konsep negara sebagai Leviathan ala Hobbes. Sebuah mekanisme yang berfungsi untuk mempertahankan ‘ketertiban’ yang layak kita pertanyakan: ketertiban bagi siapa? Atas nama siapa ketertiban ini ditegakkan? Apakah ketertiban ini tidak lain adalah alat untuk meredam jeritan yang lahir dari ketidakadilan struktural, suatu prevention of dissent yang menjadikan masyarakat tak lebih dari sekumpulan tubuh-tubuh tanpa suara, diam dalam ketakutan?
Satu hal yang patut kita sadari adalah, kekuasaan negara sering kali beroperasi di luar hukum dalam momen-momen krisis (state of exception). State of exception adalah situasi di mana hukum ditangguhkan untuk menjaga stabilitas negara, karena ada hal-hal tertentu yang memaksa negara untuk menerobos aturan yang ia ciptakan sendiri untuk mencapai tujuan.
Hal ini menjadi sesuatu yang dilematis, dengan melihat kenyataan bahwa “keadaan darurat” ini sering kali bukanlah hasil dari ancaman yang nyata, melainkan negara sendiri yang menciptakan “musuh-musuh” untuk membenarkan langkah-langkah represifnya. “Keadaan darurat,” yang seharusnya bersifat kontingen, malah dikultuskan menjadi permanen.
Ketakutan-Ketakutan Palsu
Tak ada represi yang berdiri sendiri. Ia selalu didahului dengan produksi ketakutan massal. Polisi dan tentara bukan sekadar eksekutor, mereka juga produser ketakutan. Frasa seperti “keadaan darurat”, “situasi tidak kondusif”, atau “demi keamanan nasional” adalah mantra yang menghipnotis publik agar menerima kekerasan sebagai harga yang pantas dibayar untuk ilusi ketertiban.
Begitu pula dengan cap “anarkis” yang dengan murah dilemparkan kepada mereka yang berani menentang. Kata itu telah direduksi menjadi sekadar label bagi siapa pun yang melawan, sementara maknanya yang asli—tatanan tanpa tuan, tanpa penguasa—dihilangkan dari ingatan kolektif. Ini adalah proyek untuk memonopoli tafsir tentang apa itu “keteraturan.” Sebab jika rakyat memahami bahwa “tertib” dan “adil” bukanlah sinonim, maka legitimasi negara akan hancur berantakan.
Kita melihat pola ini berulang dalam setiap bentuk represi. Mahasiswa yang turun ke jalan akan dicap sebagai “perusuh.” Buruh yang mogok kerja dianggap “mengganggu ketertiban.” Masyarakat adat yang mempertahankan tanahnya disebut “anti-pembangunan.” Polisi dan tentara tak butuh alasan yang masuk akal; mereka hanya butuh narasi yang cukup kuat untuk dijadikan justifikasi.
Narasi ini diproduksi dan didistribusikan melalui berbagai corong, mulai dari media mainstream, juru bicara pemerintah, hingga akademisi bayaran yang tiba-tiba sibuk bicara tentang “pentingnya ketertiban dalam demokrasi.” Siapa yang diuntungkan dari narasi ini? Tidak lain adalah mereka yang memiliki kuasa dan kepentingan ekonomi-politik yang menopangnya.
Pasca Reformasi, kita diperlihatkan ilusi tentang supremasi sipil, seolah-olah Indonesia telah sepenuhnya lepas dari bayang-bayang Orde Baru. Namun, ilusi ini runtuh ketika aparat bersenjata kembali merangsek ke ranah sipil dengan justifikasi keamanan. Kita melihatnya dalam upaya reaktivasi dwifungsi ABRI dalam berbagai bentuk baru, mulai dari jabatan sipil yang kembali diisi oleh militer, hingga keterlibatan mereka dalam proyek-proyek pembangunan strategis.
Mari kita berbicara secara terang-terangan: militerisme tidak pernah mati di Indonesia. Ia hanya berhibernasi, menunggu saat yang tepat untuk kembali merayap masuk. Dan kita sedang menyaksikan fase itu.
Lalu Apa?
Akhirnya, apa yang kemudian disebut keamanan oleh negara, tidak lebih dari stabilitas semu yang dijaga dengan moncong senjata. Demokrasi, yang seharusnya membuka ruang bagi kebebasan, justru dipasung dengan dalih keteraturan. Negara tidak bekerja untuk rakyat, tetapi untuk melindungi dirinya sendiri dari rakyat.
Dengan mekanisme cipta kondisi, dengan dalih stabilitas, dengan state of exception yang dikultuskan, negara telah mengubah hukum menjadi senjata dan menjadikan peluru sebagai alat legitimasi.
Sejarah telah menunjukkan bahwa perubahan tidak pernah datang dari belas kasihan penguasa. Ia datang dari rakyat yang tahu bahwa hidup dalam ketakutan bukanlah hidup yang layak dijalani. Ia datang dari mereka yang berani berkata cukup, yang menolak tunduk, yang memilih jalan yang lebih sulit karena mereka tahu bahwa di ujung jalan itu ada kebebasan yang sesungguhnya.
Dan dalam keadaan yang seperti ini, pertanyaannya bukan lagi mengapa negara bertindak represif, tetapi sampai kapan kita akan membiarkannya?
Salam hangat,
Redaksi LPM Perspektif