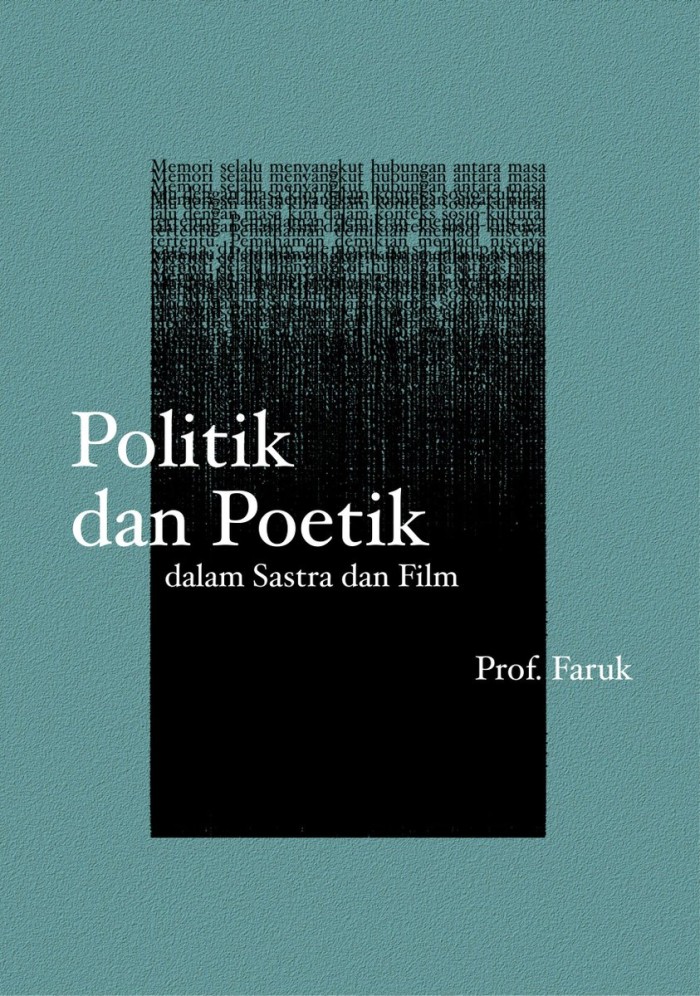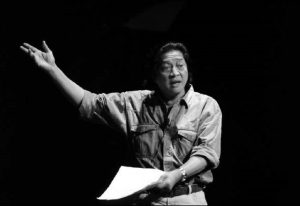Judul: Politik dan Poetik dalam Sastra dan Film
Penulis: Faruk
Penerbit: Jual Buku Sastra (Yogyakarta)
Jumlah halaman: viii + 221 halaman
Saya ingin mengawali tulisan ini dengan cerita setahun lalu di kelas yang saya ikuti di Universitas Indonesia. Seorang kolega saya bertanya kepada pengajar kami: mengapa sastra (di) Indonesia terkesan latah? Latah sebab dengan gampang muncul banyak sebutan: sastra perempuan, sastra etnografis, sastra maritim, sastra rempah, dan lain-lain. Saya lupa jawaban pengajar kami. Lagi pula, itu tidak begitu penting sebab jawaban pengajar bukanlah kebenaran final dan pertanyaan kolega saya tetap terbuka untuk dipikirkan kembali. Jawaban pertanyaan itu tampaknya tidak dapat diberikan terburu-buru karena sifatnya yang reflektif. Saya pikir, jawaban atas pertanyaan itu pelan-pelan dapat kita temukan melalui (bukan dalam) buku Politik dan Poetik dalam Sastra dan Film yang ditulis oleh Faruk (2021).
Sebagaimana judulnya, buku kumpulan esai ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama, sastra, mencakup delapan esai, sedangkan bagian kedua, film, mencakup tiga esai. Buku ini adalah kompilasi sejumlah tulisan lepas, makalah seminar, kritik sastra, dan termasuk pidato penulis sebagai guru besar ilmu sastra di Universitas Gadjah Mada. Sebagai kompilasi, saya kira pembaca bebas memulai pembacaannya dari tulisan mana pun, memulai dari awal ataupun melompat ke akhir, sebab tiap-tiap tulisannya dapat dibaca terpisah sebagai diskursus tunggal. Kendati demikian, keseluruhan tulisan ini dapat dipahami dan dijalin sebagai satu-kesatuan yang mengedepankan sebuah gagasan, yakni bagaimana sastra dan film dengan sensibilitas posmodern mengandung tarik ulur dan ketegangan antara politik dan poetik, antara tanggung jawab sosial politik dan eksperimen estetika dalam pembentukannya.
Gagasan utama buku ini terletak pada esai keduanya, “Politik dan Poetik dalam Sastra Indonesia”. Dalam esai itu, Faruk menelusuri peta kesejarahan sastra Indonesia yang dipenuhi oleh pertarungan antara seni sebagai seni dan seni dengan tujuan politik. Pertarungan tersebut tidak selamanya imbang karena ada kalanya sastra Indonesia mencurahkan diri pada urusan estetika dan poetika seperti masa setelah politik 1965, kemudian ada kalanya sastra dengan tanggung jawab sosial politik mengemuka, misalnya pada masa 1980-an. Selanjutnya, menurut Faruk, pasca-Reformasi dengan kebebasan dan demokratisasi menjadikan sastra makin plural. Yang dimaksud dengan poetika dan tanggung jawab politik pun juga makin beragam dengan membawa kepentingannya masing-masing. Jika pada masa Orde Baru, tanggung jawab politik ditujukan untuk menyoroti represi dan totalitarianisme negara (bersifat vertikal), maka tanggung jawab pada masa Reformasi bahkan bisa saling bertentangan antarkelompok (bersifat horizontal).
Meskipun demikian, saya kira pemisahan antara yang vertikal dan horizontal tidak kaku. Pergeseran yang terjadi juga tidak radikal. Kecenderungan ke arah horizontal tidak serta merta meninggalkan arah vertikal. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah karya sastra yang peristiwanya berlatar masa-masa kekerasan, seperti pembantaian negara 1965 dan kekerasan 1998. Sebut, misalnya, Laut Bercerita oleh Leila S. Chudori. Karya-karya semacam ini ditulis bahkan oleh mereka yang tidak mengalami langsung kekerasan tersebut, yang ditulis melalui riset sejarah, yang oleh Faruk disebut perkembangan ke arah posmemori. Hal ini mirip dengan film Senyap garapan Joshua Oppenheimer yang disebut oleh Faruk sebagai cerita tentang pembantaian. Sastra dan film bertendensi posmemori semacam itu, yang muncul di masa Reformasi, saya pikir adalah karya posmodern yang mencoba menghadirkan suara lain dari suara yang selama ini diartikulasikan secara tunggal oleh negara. Dengan kata lain, yang terbentuk adalah sifat vertikal.
Sementara itu, sifat horizontal dapat kita amati dari esai yang berjudul “Dari Realisme Kultural ke Realisme Magis” dan “Berburu Sastra Lokal”. Dalam esai yang pertama, Faruk membahas model realisme yang ditampilkan dalam karya-karya Umar Kayam yang mengangkat kehidupan kultural orang Jawa sebagai estetikanya. Sementara itu, dalam esai yang kemudian, Faruk memberikan refleksi konseptual bagaimana upaya-upaya untuk mengangkat atau menghidupkan sastra lokal itu dihadapkan pada tantangan. Pada masa posmodern, sastra lokal tidak bisa hanya menghadirkan kelokalan semata, tetapi juga harus diartikulasikan dengan cara yang berbeda, yang berterima di lingkup nasional bahkan global. Sebab, kata Faruk, “lokalitas tanpa globalitas adalah sia-sia”. Sebaliknya, lokalitas itu harus membentuk jaringan dengan lokalitas yang lain.
Jaringan adalah karakteristik kehidupan posmodern. Hal ini juga dibahas dalam esai “Sastra dalam Dunia Maya”. Faruk menawarkan konsep sastra dengan sensibilitas internet. Hal ini diperkuat pula oleh esai dari pidato guru besarnya, “Sastra dalam Masyarakat”, bahwa sastra posmodern adalah sastra yang tidak tertutup dengan eksistensi dirinya, tetapi terbuka dengan hadir bersamaan atau koeksistensial dengan teks-teks di luar dirinya. Jika internet memiliki karakteristik jaringan atau berjejaring, maka sastra dan film juga demikian. Teks sastra dan film berjejaring dengan teks-teks lain. Dua tulisan mengenai film sedikit banyak memperlihatkan karakteristik tersebut, yang dalam teori sastra bisa disebut hipertekstual, yakni esai yang membandingkan film Oom Pasikom dan Bajaj Bajuri juga esai tentang film Ali Topan dan Dilan.
Soal jaringan juga dieksplorasi lebih lanjut melalui esai yang secara khusus menyajikan kritik sastra terhadap novel 2020-an, yakni Aib dan Nasib karangan Minanto. Faruk mulanya menyoroti novel-novel bertendensi posmodern yang mengambil, menggunakan, dan memodifikasi cerita dan gaya penceritaan. Hanya saja, novel-novel demikian menampilkan cerita yang tampak terpisah, tidak ada koherensi, dan basi. Menurut Faruk, sastra posmodern tetap harus dan tidak anti pada satu-kesatuan, pada koherensi. Berjejaring bukan berarti asal ambil, tetapi menyatukan dan menghasilkan hubungan antarelemen. Hal itu adalah keberhasilan Aib dan Nasib. Faruk membahas struktur naratif novel tersebut untuk menjabarkan peran dan posisi tiap tokoh, kemudian menyusuri hubungan antartokoh. Pada simpulannya, dengan sekian banyak tokoh dalam novel tersebut, keseluruhan dari mereka sebetulnya berpusat pada peran internet, media, dan ponsel yang menghubungkan tokoh-tokoh tersebut. Kondisi penceritaan dalam karya semacam inilah yang oleh Faruk disebut sebagai sastra dengan sensibilitas internet, dengan sensibilitas posmodern.
Jadi, pada gilirannya, pertanyaan yang bisa kita ajukan: apakah posmodernisme adalah paradigma sastra Indonesia? Dalam esainya, “Sastra Indonesia Tanpa Paradigma?”, Faruk tidak secara ajeg meyakinkan posmodernisme sebagai paradigma meskipun kecenderungannya demikian. Yang membuat tulisannya bersikap demikian adalah kenyataan bahwa paradigma yang pernah ada dalam perkembangan sastra Indonesia tidak bertahan lama, hanya letupan, yang dapat musnah dan tergantikan. Kendati demikian, saya pikir, untuk sementara kita dapat menerima posmodernisme sebagai paradigma yang memang mengemuka.
Kembali ke pertanyaan yang saya sampaikan di awal tulisan ini, saya pikir kebudayaan posmodern pula yang memicu munculnya pluralitas—atau “kelatahan” meminjam istilah kolega saya—dalam segala hal, mulai dari definisi sastra, penyusunan tipologi dan genre sastra, hingga model kajian sastra. Pluralitas menyebabkan kepentingan menjalar dan menyebar, maka yang mengemuka menjadi beraneka. Keperempuanan mendorong sastra feminis, bahkan keberagaman seksual menumbuhkan yang disebut sastra queer. Romantisisme dan hasrat pada kelokalan memunculkan yang disebut sastra lokal, sastra pedalaman, sastra etnografi, sastra pastoral, dan seterusnya. Persoalan kepentingan terus bertumbuh dan bermacam bentuk, maka (mungkin) selama itu pula berbagai definisi dan istilah latah akan bermunculan bahkan serba cepat. Tapi, saya pikir masalah yang serba cepat tidak bisa dipahami dengan sesaat. Untuk itu, saya merekomendasikan buku Politik dan Poetik dalam Sastra dan Film dalam rangka memahami persoalan itu secara konseptual dan paradigmatik.