…Melampaui imaji di tengah hancurnya dunia
Di setiap sudut, ada sipir dan tentara…
— Terapi Minor – Obscura
Kita tahu, sejarah punya kebiasaan buruk. Ia sering datang kembali dengan wajah yang lain.
Pada tahun 1978, selepas gelombang demonstrasi mahasiswa yang menuntut pembaruan politik, pemerintah Orde Baru meluncurkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus yang diikuti pembentukan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) melalui kebijakan yang diteken oleh Daoed Joesoef, Menteri Pendidikan saat itu. Kebijakan ini mengandaikan bahwa kehidupan kampus masa itu telah melenceng dari jalurnya, maka perlu kiranya kehidupan itu dinormalkan. Normalisasi ini dimulai dengan membubarkan organisasi atau membatasi kegiatan politik mahasiswa. Singkatnya, pemerintah saat itu berupaya mendesain ulang ruang kampus menjadi steril dari konflik gagasan, membuang politik ke luar pagar universitas. Pasca kebijakan itu diterapkan, praktis sudah ruang sipil di perguruan tinggi dikerdilkan.
Untuk memahami kelahiran NKK/BKK, perlu kita melakukan pembacaan mundur setidaknya satu dekade. Sejak naiknya Mayor Jenderal Soeharto menjadi presiden pada tahun 1966, faksi militer memantapkan diri sebagai kekuatan politik utama melalui formalisasi doktrin Dwifungsi ABRI, yang memberi tentara peran ganda. Mempertahankan negara sekaligus mengelola pemerintahan sipil. NKK/BKK lahir sebagai konsekuensi logis dari logika berpikir ala militer, yang entah mengapa sangat mencintai stabilitas. Kampus dengan sejarah panjangnya sebagai tempat lahirnya gerakan sosial dan politik, dipandang sebagai wilayah bergejolak nan tak stabil yang harus “diamankan.”
Sejak awal kemerdekaan, kampus di Indonesia bisa dibilang menjadi salah satu pusat gerakan politik. Sebagai bagian dari masyarakat yang menjadi generasi terdidik dan cukup sadar dengan kondisi Indonesia masa itu. Tahun 1966, mahasiswa turun ke jalan menuntut Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) yang menjadi salah satu rentetan peristiwa yang mengiringi jatuhnya Orde Lama. Orde Baru awalnya dekat dengan mahasiswa, dan banyak aktivis yang percaya bahwa pemerintahan baru ini akan membuka ruang demokrasi yang sempat hilang di paruh akhir kepemimpinan Soekarno. Namun hubungan itu mulai retak pada tahun-tahun selanjutnya, setidaknya sejak tiga tahun kepemimpinan Soeharto, saat sang jenderal mulai menampakkan tabiat aslinya. Kebijakan ekonomi yang pro-modal asing, ketimpangan pembangunan, korupsi, serta “sifat” kerajaan yang ternyata tak berubah, menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat yang terlanjur menaruh harapannya pada Orde Baru. Faktual, masyarakat terjebak pada kondisi keluar mulut harimau, masuk mulut buaya.
Sepanjang medio 1970-an, mahasiswa terus mengkritik kebijakan pemerintah masa itu. Gelombang protes besar banyak terjadi. Salah satu isu utamanya adalah penolakan terhadap pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan berikutnya. Demonstrasi terjadi di berbagai kota seperti Bandung, Yogyakarta, Jakarta dan Malang. Rentetan aksi ini termasuk pada aksi seruan Golongan Putih (Golput) pada jelang pemilu 1971 dan meletusnya peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974 di Jakarta. Pada tahun-tahun setelahnya, muncul pula gelombang protes dengan tuntutan yang kurang lebih sama hingga tahun 1978.
Peristiwa Malari menjadi salah satu titik balik. Pemerintah bereaksi cepat. Aparat keamanan masuk ke kampus-kampus, menjebloskan mahasiswa ke penjara, dan membubarkan kegiatan-kegiatan yang dianggap “subversif”. Bagi pemerintah, rentetan “kerusuhan” yang terjadi adalah bukti bahwa mahasiswa bisa menjadi sumber instabilitas nasional. Meski demikian, belakangan diketahui bahwa meletusnya peristiwa Malari, tak lain merupakan hasil campur tangan dari elit militer yang turut memobilisasi kerusuhan.
Rentetan peristiwa di atas berhasil membuat pemerintah saat itu kepanasan. Walhasil pada tahun 1974, pemerintah mulai mewajibkan mahasiswa untuk meminta izin kepada pihak rektorat saat akan melakukan kegiatan. Melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayan No. 028/1974, ruang mahasiswa dipersempit. Hal itu jelas membikin mahasiswa marah, dan membuat mereka memutuskan untuk menolaknya—meski pada akhirnya suara mereka tak digubris oleh pemerintah. Hal ini berbuntut pada dibekukannya dewan-dewan mahasiswa di kampus-kampus, serta pembatasan aktivitas mahasiswa pada hal yang sifatnya akademik dan rekreasional belaka. Pembekuan itu dilakukan oleh unsur militer, melalui SK No. 02/Kopkam/I/1978 pada tahun 1978 yang dkeluarkan oleh Pangkopkamtib Jenderal Sudomo. Disusul dengan pembatasan ranah mahasiswa dan pembekuan dewan mahasiswa yang diteken oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Instruksi Menteri P dan K No. I/U/1978. Represi ini diperparah dengan semakin massifnya perburuan yang dilakukan pemerintah yang menyasar basis-basis mahasiswa yang dianggap vokal.
Lantas naiklah Daoed Joesoef menjadi Menteri Pendidikan yang mengesahkan kebijakan NKK/BKK yang menyatakan bahwa seluruh tindak mahasiswa yang keluar dari ranah akademik dianggap tidak sah. Melalui kebijakan inilah Tentara (ABRI pada saat itu) mulai masuk serta menduduki kampus-kampus untuk melakukan penyisiran dan penertiban, atas nama stabilitas negara. Organ-organ mahasiswa dijinakkan, diskusi mahasiswa dibuyarkan, dan gerakan mahasiswa direpresi dengan berbagai cara. Mulai dari pelarangan mengedarkan bacaan-bacaan yang dianggap terlarang, hingga penangkapan dan kriminalisasi tanpa pengadilan.
Maka tak bisa ditampik, sejak saat itu tradisi kemiliteran di ruang sipil dan “ruang steril” di kampus-kampus tumbuh subur bak cendawan di mangsa hujan. Posisi-posisi penting banyak diisi oleh kalangan militer, pun pengetahuan diposisikan sebagai anak perempuan kestabilan negara yang tak boleh sedikitpun mengusik kursi penguasa. Ilmu pengetahuan seolah cantik jika patuh, terkutuk bila membangkang. Kondisi historis itu masih bisa kita rasakan, bahkan setelah Reformasi berjalan hampir 28 tahun.
Barangkali yang cukup dirugikan adalah diskursus ilmu sosial di Indonesia, yang sempat akrab dengan kajian-kajian “kiri” dan kerakyatan. Dibonsailah ia dalam satu pot kecil atas nama kestabilan negara. Dan inilah yang menjadi sebab-musabab kemacetan panjang, membuatnya mandek di ranah yang itu-itu saja. Bahkan kebiasaan intelektual yang terpelihara di masa itu masih terasa membayangi hingga kini. Di bawah naungan Orde Baru, sosiologi misalnya, tak lagi bergerak liar mencari kemungkinan-kemungkinan baru, melainkan dirangkul erat untuk mengawal stabilitas politik.
Empat nama besar sosiolog: Selo Soemardjan, Soerjono Soekanto, Nasikun, dan Sayogyo, menjadi figur sentral yang, meskipun berbeda metode dan perhatian, berbagi satu rumpun praxis yang sama yaitu mengamini floating mass ala Ali Moertopo, sebuah siasat menjauhkan rakyat dari politik demi keteraturan. Kerangka pikir mereka bertumpu pada sistem Talcott Parsons dan fungsionalisme Durkheim, menjauhi Weberian apalagi Marxis yang dianggap mengancam. Dari sana, sosiolog-sosiolog kiri seperti Arief Budiman dan George Junus Aditjondro disingkirkan dari arus utama, dan sosiologi pun berubah dari disiplin kritis menjadi alat pemelihara kekuasaan. Bahkan, negara menganugerahi Selo Soemardjan gelar “Bapak Sosiologi Indonesia”, seolah menyegel arah perjalanan disiplin itu.
Padahal, di banyak belahan dunia, ilmu sosial berkembang pesat di bawah pengaruh dan perdebatan yang tak bisa dilepaskan dari warisan Marxisme. Nama Karl Marx menjadi figur yang hampir mustahil diabaikan dalam peta besar sosiologi dunia. Baik sebagai inspirasi maupun sebagai musuh yang layak dilawan, Karl Marx menjadi figur yang hampir mustahil diabaikan. Bahkan teori-teori kontemporer yang lahir untuk mengkritik atau membongkar Marxisme tetap menempatkannya sebagai titik tolak pembahasan. Di Eropa, Amerika Latin, hingga sebagian Asia, sosiologi dan ilmu politik justru bertumbuh subur di atas interaksi dialektis dengan teori kelas, kritik kapitalisme, dan analisis materialis sejarah. Namun di Indonesia, sejarah mengambil jalannya sendiri. Dalam buku-buku pengantar seperti karya Soerjono Soekanto, nama Marx bahkan tidak hadir sebagai tokoh penting.
Hari ini, dua dekade lebih setelah reformasi, ilmu sosial memang mulai menerima kembali “kekritisan” sebagai bagian dari kurikulumnya, tetapi bekasnya masih terasa. Ia meninggalkan noda seperti flek dalam paru-paru hitam perokok kretek sejak SMA. Setidaknya bagi saya seorang mahasiswa sosiologi tahun ketiga, saya masih melihat bagaimana setelah reformasi, “kekritisan” memang mulai kembali, tapi datang ia seperti transplantasi organ pada tubuh yang sudah lama menolaknya. Yang penting dicatat adalah warisan itu tak berhenti semata di tataran teori atau kurikulum. Turut menjalar pula ia ke dalam kebudayaan kampus itu sendiri. Katakanlah, senioritas yang memposisikan mahasiswa baru sebagai objek penundukan, perpeloncoan yang dibungkus sebagai “pembinaan karakter,” dan gaya-gaya kemiliteran yang menuntut ketaatan mutlak dengan dalih kedisiplinan.
Pasca-Reformasi, banyak yang mengira warisan ini akan terhapus. Militer kembali ke barak, NKK/BKK dicabut, dan kampus dianggap kembali menjadi ruang bebas. Namun kenyataannya, mutan (baca: kultur) yang diwariskan Orde Baru tidak (atau agar terlihat optimis, belum) hilang. Mutan itu beradaptasi. Mutan-mutan itu adalah sisa-sisa logika floating mass (baca: depolitisasi masyarakat) dan disiplin Orde Baru yang ditanamkan selama puluhan tahun. Hingga hari ini, bayangan warisan itu masih tampak di berbagai kampus: dalam tata cara organisasi yang hierarkis, dalam bahasa perintah yang membungkam kritik, bahkan dalam kebiasaan akademik yang tak egaliter dan cenderung feodal.
Kini, dengan naiknya Prabowo ke kursi presiden, seorang yang masa lalunya lekat dengan dunia militer Orde Baru dan tuduhan keterlibatannya dalam pelanggaran HAM berat, mulai dari penculikan aktivis pro-demokrasi 1997–1998 hingga operasi militer di Timor Timur, kontinuitas itu menemukan momentumnya. Retorika tentang stabilitas, ketertiban, dan nasionalisme kembali mengemuka, sementara ruang untuk kritik sosial terasa makin sempit di tengah iklim politik yang semakin sensitif terhadap perbedaan pandangan.
Apa yang Bisa Kita Pelajari?
Kita kerap mengulang adagium bahwa “sejarah berulang”. Namun, jika ditelusuri secara lebih teliti, sejarah tidak pernah berulang; ia menetap. Yang berulang adalah diri kita yang bergerak di dalam lintasan yang sama, tak pernah melampaui orbit yang diwariskan. Orde Baru tak berakhir pada 1998, ia masih menjelma rezim pengetahuan dan formasi sosial yang belum pernah kita tinggalkan. Ia membentuk institusi, bahasa, kebiasaan, bahkan imajinasi politik kita.
Sejak hari pertama kita menjajaki kampus, pola itu masih terendus bau busuknya. Lihat saja bagaimana kita disambut dalam satu teater konyol yang tak substansial isinya, lengkap dengan sipir dan tentaranya. Seremoni penyambutan yang saya sendiri sudah muak mendengarnya. Belum lagi saat kita mulai masuk ke dalam kehidupan sehari-harinya, kita akan dihadapkan pada ratusan atau bahkan ribuan omong kosong yang membikin kita pusing muntah-muntah karena tak penting sebenarnya.
Pola yang sama juga masih beroperasi bahkan dalam skala negara. Kampus, dengan demikian, tidak sepenuhnya berbeda dari struktur sosial yang melingkupinya. Ia adalah miniatur negara, dengan birokrasi, hierarki, dan logika kekuasaan yang sama. Prabowo Subianto memperlihatkan kontinuitas tersebut secara terang-benderang: revisi UU TNI tahun 2025 yang mengizinkan perwira aktif menduduki jabatan sipil di 14 lembaga negara, membuka jalan bagi reaktualisasi dwifungsi ABRI yang dulu menopang Orde Baru. Kita bisa melihatnya pula dalam mobilisasi militer besar-besaran dalam ruang-ruang sipil macam pengelolaan pangan, farmasi, bahkan layanan publik. Sementara kritik dibatasi melalui revisi narasi sejarah dan gaya intimidatif anti-intelektual terhadap jurnalis maupun akademisi.
Maka, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa melawan tidak berarti menunggu “masa depan” datang, sebab kita masih terperangkap di masa lalu. Dalam hemat saya, untuk melakukan perlawanan diperlukan setidak-tidaknya 3 syarat. Kesadaran historis adalah syarat pertama, perbekalan epistemik (dalam artian membekali diri dengan kerja-kerja pengetahuan yang cukup) adalah syarat kedua, dan tindakan kolektif adalah syarat ketiga. Dua syarat awal adalah necessary condition yang tanpanya, perlawanan tak mungkin bahkan dimulai. Tetapi untuk menjadikannya nyata, kita memerlukan syarat ketiga yang berfungsi sebagai sufficient condition untuk mengubah kesadaran dan pengetahuan menjadi daya yang bergerak, terarah, dan berdaya ledak. Dan kalau kita serius mendaku diri sebagai akademisi (dalam arti yang paling sederhana yaitu orang yang berpikir) maka minimal yang bisa kita lakukan adalah tidak ikut mengulang kedunguan yang sudah didokumentasikan dengan baik oleh sejarah, dalam artian kita harus melawan itu semua.
Akhirul kalam, Sejarah tiada berulang. Menunggu ia, mengurung kita dalam tembok yang tak kasatmata, selayaknya menunggu Godot, tembok itu takkan runtuh hingga kita sendiri yang merobohkannya.
La historia me absolvera!



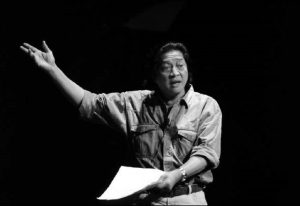









Hmmmmm