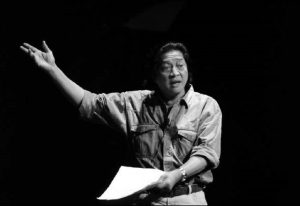There’s no such thing as free lunch…
Dalam esai berjudul On Bullshit, Harry Frankfurt membedakan antara kebohongan dan omong kosong. Pembohong, seberapapun culasnya, masih menghargai kebenaran—karena ia perlu tahu apa yang benar untuk bisa memelintirnya. Tapi pencerita omong kosong tidak peduli sama sekali tentang benar atau salah. Mereka tidak berusaha menutupi kebenaran, juga merasa tidak perlu berurusan dengannya.
Singkatnya, seorang pencerita omong kosong tak peduli pada kebenaran maupun kebohongan. Yang terpenting baginya adalah kesan yang ia tinggalkan, dampak yang ia hasilkan, serta seberapa jauh narasinya dapat menggiring publik dalam delusi yang ia ciptakan.
“Lalu, bagaimana jika cara bernegara mulai dibangun di atas omong kosong?”
Kita melihat gejala itu hari ini, dalam pemerintahan yang menasbihkan dirinya sebagai penguasa, yang tak peduli pada realita sebenarnya. Kami menyebutnya sebagai Rezim ‘Omon-Omon’, suatu rezim omong kosong. Alasannya tidak sesederhana karena istilah itu pernah meluncur dari mulut pemimpinnya, melainkan karena segala kebijakan yang ia gulirkan tak lebih dari upaya menimbulkan impresi semu tentang kemajuan.
Salah satu manifestasi paling nyata dari rezim omong kosong ini terlihat dalam kebijakan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi tak lagi menjadi pilar utama. Sebaliknya, pendidikan diletakkan sebagai program pendukung di tengah prioritas lain yang lebih sedap didengar dan lebih mudah dijual ke massa yang lapar akan gestur kepedulian.
Ketika pemerintah memangkas anggaran pendidikan demi program Makan Bergizi Gratis (MBG), kita melihat betapa dangkalnya cara bernegara para pemimpin kita. Sebuah negara yang mendaku ingin membangun “Indonesia Emas 2045”, tetapi tak ragu memangkas dana pendidikan yang seharusnya menjadi lokomotif kemajuan intelektual bangsa.
Sementara dana Rp171 triliun digelontorkan untuk program Makan Bergizi Gratis yang populis dan tidak menyentuh akar permasalahan, kampus-kampus “dipaksa” produktif dalam keterbatasan. Tak ada anggaran tambahan untuk memperbaiki fasilitas penelitian. Tak ada ancang-ancang untuk menekan biaya kuliah yang kian mencekik. Tak ada perhatian bagi kesejahteraan dosen, yang kelelahan mengejar angka kredit publikasi, bergelut dengan birokrasi, dan menunggu tunjangan kinerja yang cair entah kapan.
Situasi ini diperparah dengan kebijakan otonomi kampus melalui status PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum). Alih-alih memberikan kebebasan akademik yang sejati, kebijakan ini justru membuka pintu lebar bagi privatisasi terselubung. Kampus bukan lagi ruang produksi pengetahuan, melainkan mesin raksasa yang menggerus tenaga kerja akademik demi keuntungan segelintir elit birokrasi.
Lebih mengkhawatirkan lagi, terdapat dorongan bagi universitas untuk terlibat dalam bisnis ekstraktif seperti pengelolaan tambang. Langkah ini bukan sekadar mengancam integritas ilmiah, tetapi juga memaksa universitas merangkul logika pasar dengan cara yang paling vulgar.
Akhirnya, PTN-BH, dengan segala wacananya, telah menjadi kendaraan sempurna bagi masuknya neoliberalisme ke dalam sistem pendidikan tinggi. Mahasiswa sebagai pelanggan (yang banyak dikecewakan tentunya), dosen sebagai tenaga kerja yang dibayar murah, dan ilmu pengetahuan sebagai komoditas yang dijual mahal untuk kepentingan industri dan kapital.
Akademisi di Negeri yang Tak Mau Mendengar
Barangkali, kapasitas seorang pemimpin bukan hanya ditakar dari kegarangannya saat berpidato, tetapi juga dari ketajaman nalar berpikirnya dan keluasan hatinya dalam menerima kritikan. Tetapi apa jadinya jika kritik dianggap sebagai gangguan, dan para ilmuwan yang mengemukakan pendapat justru dicemooh; diperlakukan layaknya musuh negara?
Sikap pemerintah terhadap kritik akademik menjadi cermin yang sempurna dari rezim omong kosong ini. Suatu rezim anti-kritik, anti-intelektual. Dalam logika kekuasaan yang rezim ini bangun, skeptisisme terhadap kebijakan negara diperlakukan layaknya kejahatan yang mencoreng muka bangsa.
Hal ini tampak jelas ketika Prabowo merespons kritik akademisi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alih-alih menanggapi substansi kritik dengan argumen rasional, ia justru mereduksi skeptisisme akademik dengan sinis: mempertanyakan apakah profesor-profesor itu punya hati. Nada sinis itu seolah menegaskan bahwa rasionalitas kini tidak lagi penting, bahwa perdebatan kebijakan bisa dikalahkan dengan retorika sentimental. Kritik dikecilkan menjadi sejenis kepekaan moral yang bisa diukur secara dangkal.
Sikap anti-kritik dan anti-intelektual ini semakin kentara dalam kebijakan perkebunan sawit. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Prabowo secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia perlu menambah penanaman kelapa sawit, sambil menepis kritik tentang deforestasi dengan logika yang sangat simplistik. Logika akademik dipertentangkan dengan keyakinan pribadi, kajian ilmiah disepelekan, dan para ilmuwan diremehkan. Bagi rezim ini, argumen tidak lagi dinilai dari bobotnya, tetapi dari apakah ia mendukung narasi kekuasaan atau tidak.
Mungkin bagi Prabowo, kritik akademisi hanyalah “omon-omon.” Sebab, untuk apa mendengar jika realitas bisa dibentuk lewat retorika? Apa perlunya kajian ilmiah jika pidato berapi-api bisa menggantikan fakta?
Inilah yang terjadi di negeri yang tak mau mendengar. Sebuah republik yang konstitusinya menjanjikan demokrasi, tetapi dalam praktiknya, kritik dilihat sebagai serangan. Padahal, negara yang matang lahir bukan dari puja-puji, tetapi dari dialektika dan keberanian bertanya.
Quo Vadis, Universitas Brawijaya?
Ketika kebenaran kehilangan maknanya dan kebijakan hanya menjadi sirkus belaka, maka perguruan tinggi memiliki dua pilihan: tunduk pada logika ‘omon-omon‘ yang meludahi semangat pendidikan, atau menjadi mercusuar intelektual yang mengedepankan kebenaran ilmiah dan kritis terhadap kebijakan negara. Namun, jika kita melihat sikap PTN di Indonesia—termasuk Universitas Brawijaya (UB)—maka jawabannya semakin jelas: alih-alih berpihak pada kebenaran, kampus lebih memilih jalan aman, jalan yang tidak mengguncang status quo; jalan yang lebih menguntungkan.
Sebagai salah satu PTN-BH, UB telah bergerak semakin jauh ke arah komersialisasi pendidikan. Kebijakan peningkatan kuota mahasiswa jalur mandiri, kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta pola-pola kapitalisasi lainnya, menunjukkan bahwa kampus ini tengah dikelola dengan logika korporasi neoliberal.
“Lalu bagaimana dengan fakultas kita? Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya?“
Ironisnya, fakultas kita yang seharusnya menjadi benteng pemikiran kritis, acapkali terjebak dalam eufemisme birokratis dan retorika kosong. Isu-isu krusial seperti kekerasan seksual, komersialisasi pendidikan, hingga represi terhadap gerakan mahasiswa lebih sering ditanggapi dengan pernyataan normatif tanpa tindak lanjut yang nyata. Jika FISIP UB tidak segera mempertegas keberpihakannya terhadap kebebasan akademik dan keadilan sosial, maka fakultas ini tak ubahnya hanya menjadi ornamen intelektual di dalam universitas yang semakin kehilangan jati dirinya.
Saat senjakala intelektual terpampang nyata, UB dan fakultas-fakultasnya harus berani mengambil sikap. Apakah mereka akan tetap menjadi alat legitimasi bagi rezim yang membangun kebijakan di atas omong kosong? Ataukah mereka akan berdiri sebagai institusi yang setia pada prinsip akademik dan keberpihakan terhadap kebenaran?
Oleh sebab itu kami bertanya: “Quo vadis, Universitas Brawijaya? Ke arah mana perguruan tinggi ini akan melangkah?”
Karena pada akhirnya, masa depan sebuah bangsa tidak dibangun di atas omong kosong, ia tak lahir dari omon-omon.
Selamat merenung!
Salam hangat,
Redaksi LPM Perspektif