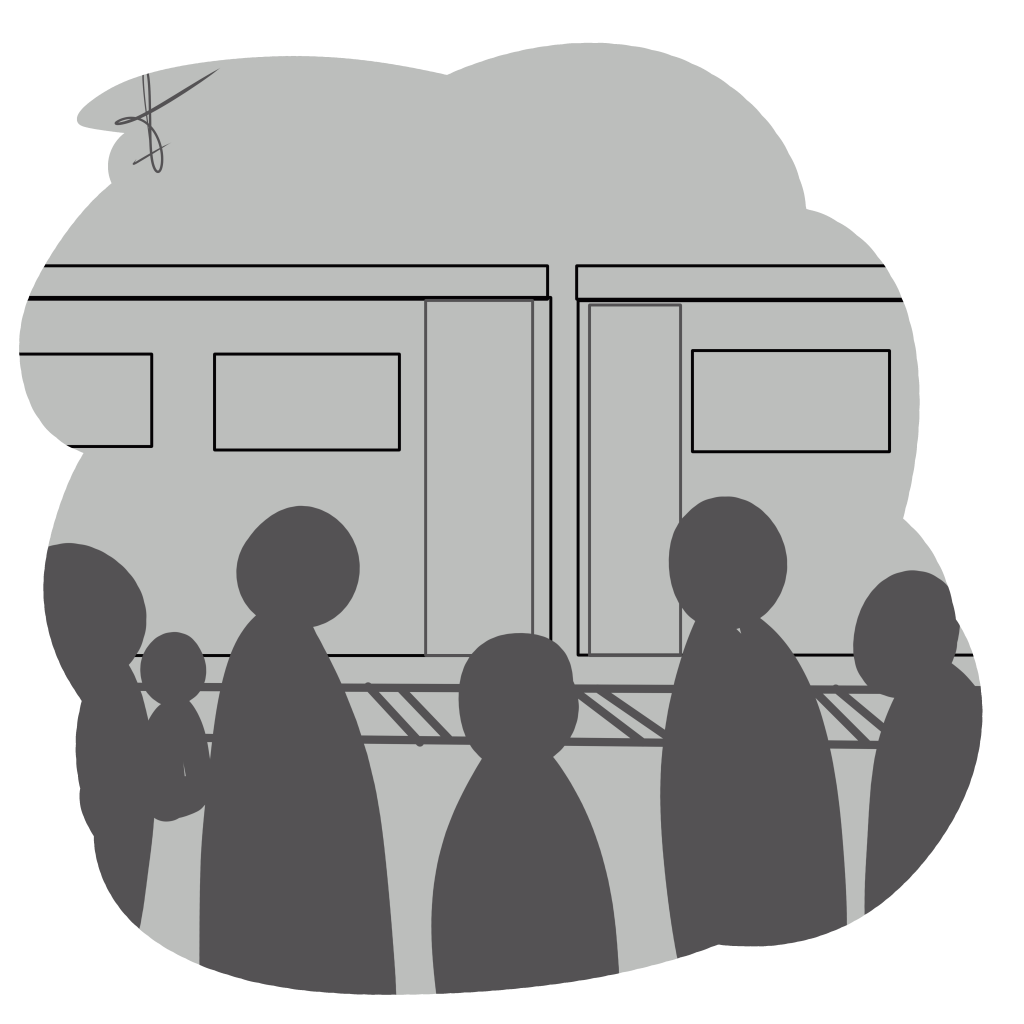Oleh: Christanti Yosefa
Rusdi berdiri diam mengamat-amati para penumpang yang sedang menunggu kereta di stasiun Blimbing. Sudah sejak setengah jam yang lalu stasiun itu ramai dipadati penumpang, padahal hari masih baru saja mencicip pagi. Petugas tiket terlihat masih mengantuk, berkali-kali menguap dan meneguk kopi yang kini sudah tinggal separuh. Orang-orang terlihat tidak peduli. Sebagian sibuk bermain ponsel, sebagian lagi sibuk bercengkrama. Beberapa dari mereka ada yang tertidur, ada yang sedang membaca koran. Petugas loket sedang kewalahan menjelaskan aturan kereta api yang baru pada seorang ibu-ibu paruh baya yang tak kunjung mengerti. Ibu-ibu itu sedikit gusar sebab tiket yang ingin dibeli telah habis karena ia tidak tahu jika tiket sudah bisa dipesan sejak jauh-jauh hari.
Rusdi berdiri diam di pojok stasiun kecil itu, mengawasi setiap orang dibawah topi hitam kumalnya. Sejak tadi ia ingin sekali menyalakan rokok untuk mengusir dingin, tapi ia tak mampu. Dibalik masker putih tipisnya, giginya mulai bergeletuk. Wajahnya sedikit pucat, dan matanya liar mengawasi setiap orang.
Dari kejauhan ia memang tampak tenang, tapi hatinya sama sekali tidak bisa diam. Kalau saja ada orang yang sedikit lebih peka berdiri di sampingnya, ia pasti bisa mendengar suara jantungnya yang berdebam begitu keras.
Sepuluh menit menuju kedatangan kereta. Rusdi semakin tidak sabar. Para penumpang mulai memadati satpam yang sudah melek sempurna. Akan tetapi, sang satpam mendapat panggilan dari pengawas dan segera berdiri meninggalkan mejanya. Tak lama kemudian terdengar pengumuman di pengeras suara bahwa kereta mengalami keterlambatan selama sekitar setengah jam karena harus mendahulukan kereta eksekutif yang mengalami kendala sebelumnya. Para penumpang menghela napas panjang. Banyak dari mereka bersungut-sungut dan mengeluhkan profesionalitas pihak kereta api. Sementara di pojok stasiun kecil itu Rusdi semakin ketar-ketir.
Setengah jam lagi, pikirnya. Mungkin aku bisa keluar dan menghirup udara segar.
Rusdi pun memutuskan untuk keluar sejenak dan berjalan-jalan di sekitar stasiun tersebut. Stasiun Blimbing bukanlah stasiun besar, hanya beberapa kereta yang melewatinya. Stasiun itu juga tidak terlalu sibuk, begitupun pengawasannya yang kurang ketat. Beberapa orang yang sama datang silih berganti untuk urusan pekerjaan, karena itu kebanyakan dari mereka secara rutin menunggu kereta api di stasiun tersebut.
Jika boleh jujur, ini kali pertama Rusdi memasuki stasiun. Sejak kecil ia selalu bertanyatanya bagaimana rasanya menaiki kereta api. Akan tetapi, jauh dalam lubuk hatinya Rusdi menyimpan luka lama terhadap stasiun dan kereta api. Dan, sekalipun ia sangat penasaran bagaimana rasanya naik kereta api dan bagaimana cara kerja stasiun, ia tak sudi menaikinya barang sekali saja. Ia bersumpah tidak akan menaiki kereta api dan meninggalkan segala pertanyaannya tentang kereta api sebagai sebuah misteri yang lebih baik dikubur dalam-dalam, beserta seluruh luka lama yang ia miliki tentang hal tersebut.
Rusdi membenci kereta api bahkan sebelum ia pernah menaikinya. Kereta api baginya adalah pemisah, transportasi aneh yang memotong seluruh jalan dengan relnya yang super panjang dengan tampang tak bersalah.
Rusdi menyalakan rokoknya. Ia menghisap rokok itu dengan tatapan getir. Seorang kakekkakek di sampingnya menepuk pundaknya seraya berkata, “Boleh pinjam koreknya, Dik?” Rusdi terkejut. Ia menoleh dan tersenyum, “Nggih, Pak.” Ia menyerahkan koreknya dengan sedikit menunduk.
“Mau kemana?”tanya Kakek itu.
“Surabaya, Pak. Gedongan.”
“Oh, kerjaan ya? Setiap minggu kesini dong?”
“Oh, bukan, Pak. Cuma ke kenalan saja.”Ia tersenyum pelan.
“Oalah…” Kakek itu manggut-manggut. Rusdi diam saja. Ia berharap Kakek itu cepat berhenti agar ia tak perlu bohong lagi. Namun kakek itu malah bicara panjang lebar mengenai sistem kereta api dan kehebatannya sekarang. Rusdi semakin ciut. Sepuluh menit sudah kakek itu
bicara panjang lebar. Rusdi diam saja sembari sesekali menanggapi, “Oh iya, Pak?” atau “Eh, begitu rupanya.”
Kakek itu pun selesai bicara saat rokok Rusdi yang tadi separuh itu habis. Ia berpamitan masuk ke dalam stasiun. Kakek itu tersenyum dan mengangguk.
Di dalam stasiun, Rusdi kembali termenung. Ia berpikir mengenai banyak hal, mengapa ia ada disini, mengapa ia menginjakkan kaki di tempat yang telah ia kutuk bertahun-tahun. Ibarat luka lama yang diperban, perban itu ia buka pelan-pelan. Bukannya membaik, luka itu justru membusuk dan nanahnya semakin dalam. Secara sadar Rusdi telah menambah luka itu dengan menyiramkan air raksa. Ia sakit luar biasa.
Hingga usia lima tahun, sejauh yang dapat diingatnya, Rusdi mengagung-agungkan sosok ayahnya sebagai pahlawan dan penjelajah. Sedikit lebih besar ia menyandingkannya dengan Columbus. Namun, perlahan-lahan, pujaan itu meluruh seiring berjalannya waktu. Ayahnya yang seorang masinis tak pernah pulang saat ia berusia 7 tahun, dan beberapa tahun sejak itu, ibunya mulai jatuh sakit. Selama ditinggal ayahnya Rusdi dan ibunya hidup sengsara. Makan sehari dua kali saja, itupun jika mereka sedang cukup. Ibunya rela bekerja apa saja, tukang cuci, setrika, penjual gorengan, semua ia lakukan demi Rusdi. Di usia empat belas tahun, ibunya meninggal. Rusdi kehilangan arah hidupnya. Saat itulah, semua kenangan ayahnya sirna tergantikan oleh benci dan kemarahan yang luar biasa, akumulasi rasa lelah dan rindu yang tak kunjung padam. Dari sosok Columbus, sosoknya telah berganti menjadi pengkhianat. Rusdi membencinya dan menyalahkannya untuk apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Ayah Rusdi dulu sangat menyayangi keluarga kecilnya. Sekalipun pulang dua hari sekali, ia selalu membawa sesuatu, entah itu cerita, martabak atau mobil-mobilan. Mereka hidup dalam kesederhanaan yang membahagiakan. Hingga suatu hari, ayahnya tak pernah kembali. Pencarian? Tak pernah mereka berhenti mencari. Ibunya bertanya kesana kemari, mengirim surat, menitip pesan pada masinis lain. Tapi semua itu tetap tak terbalas. Rusdi merasa tak pernah ada pertengkaran di keluarga mereka. Sampai suatu hari seorang masinis teman ayahnya datang dan mengabarkan bahwa ayah Rusdi telah pindah ke Jawa Tengah dengan keluarga barunya. Rusdi tak pernah tahu cerita ini sampai usianya 12 tahun, itupun tak sengaja ia dengar dari tetangganya yang kebetulan ibu dari teman sekelasnya yang selalu mengejeknya.
Sejak hari itu, Rusdi melihat ibunya sama sekali lain. Ia tak lagi melihat ibunya dengan tatapan yang sama. Ia menatap mata ibunya, mendapati kesungguhan, keharuan, kekuatan, dan rahasia yang tak pernah ia sadari tersibak di kedalaman matanya. Detik itu juga, Rusdi menangis tersedu-sedu dan langsung menghambur ibunya. Ibunya kebingungan, tapi Rusdi tak memberitahukan alasannya. Saat itu juga, hidupnya jungkir balik. Sosok pahlawan dalam hatinya telah tergantikan. Sosok pahlawan lama itu ingin sekali ia injak-injak, ia buang, dan tak pernah ia lihat lagi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengkhianat itu ia haramkan, tak sudi ia sentuh, dan ia kubur rapat-rapat.
Rusdi kembali bertanya-tanya, tercenung dalam hatinya atas segala misteri dan pertanyaan yang tak pernah berhasil ia temui jawabannya. Sejak ibunya meninggal Rusdi hidup sendiri, mengamen, menjual layangan, sekolah pun ia tak tentu lagi. Satu saja kesalahan dari pengkhianat itu telah merusak segalanya. Termasuk alasan mengapa sekarang ia berdiri memojok disini dan hampir menangis putus asa.
***
Satpam kembali tepat ketika pengumuman kedatangan kereta akan segera tiba. Dengan tangan gemetar Rusdi menyerahkan karcis dan KTP-nya, lalu memasuki gerbong kedua tempat duduknya. Tak disangka, disebelahnya duduk kakek-kakek cerewet yang ia temui di depan stasiun tadi. Kakek itu terlihat senang saat melihat Rusdi menduduki bangku disampingnya.
Sepanjang perjalanan kakek itu terus bicara dan Rusdi merasa kelelahan. Di stasiun berikutnya, kakek itu berangsur berhenti dan merasa mengantuk. Tak lama kemudian ia tertidur. Saat itulah Rusdi mulai beraksi. Ia memasukkan tangannya ke saku kakek itu. Di dalam saku tersembul dompet kulit yang sama tuanya dengan kakek itu. Tiba-tiba kelebat bayangan mengapa ia memilih kereta api dan mencopet didalamnya terlintas. Ia berencana untuk mencopet di dalam kereta karena baginya ia akan lebih mudah untuk keluar. Lagipula, dalam kereta semua orang lebih mungkin tertidur. Kereta juga terkenal sebagai moda transportasi yang aman. Dengan mudah ia bisa keluar tanpa dicurigai.
Peluh Rusdi menderas, jantungnya berdebum setengah mati. Kebetulan dua orang perempuan di depannya juga sedang tertidur. Ia semakin merasa ketakutan walau sedikit lega. Ini
kali pertama Rusdi mencopet. Sekalipun besar di jalanan, Rusdi pantang mencopet. Ia bekerja serabutan. Namun khusus kali ini, ia tak punya pilihan lain.
Dengan satu kali gerakan dompet itu telah berpindah tangan. Kereta bergoyang mengikuti ritme rel. Rusdi lega bukan main. Tak disangka mencopet ternyata semudah itu walau memerlukan adrenalin tinggi. Pengumuman pemberhentian stasiun berikutnya terdengar. Pelan-pelan Rusdi bangkit dan menuju ke pintu gerbong.
Saat kereta hampir berhenti dan kakinya sedikit lagi menapak tanah, seorang petugas kereta menarik kerah bajunya dari belakang dengan tatapan tajam.
***
Kakek cerewet itu terkejut setengah mati. Ia menunjuk-nunjuk Rusdi dengan marah sembari mengeluarkan kata-kata kasar. Tindakan mencolok itu terlihat oleh orang hampir seluruh stasiun. Petugas berusaha menenangkan kakek itu dan membawa Rusdi menuju kantor. Rusdi sudah putus asa. Ia diiring menuju kantor dan dicecar berbagai macam pertanyaan yang lebih terdengar seperti tuduhan. Rusdi kemudian dibawa ke kantor polisi dan untuk sementara diamankan di dalam sel.
Sembari meringkuk di pojok sel penjara Rusdi berpikir keras. Bagaimana perasaan istrinya, bagaimana anaknya melihat dirinya seperti ini? Istri Rusdi pasti sekarang sedang khawatir menunggu di depan rumah, mondar-mandir sembari menenangkan anak mereka yang menangis tiada henti. Rusdi tak membawa ponsel, pun dompet. Ia memohon untuk menghubungi keluarganya. Polisi menepis permintaannya setidaknya sampai kakek itu memutuskan untuk menghukum atau memaafkan Rusdi.
Jauh di daerah kumuh kota Malang, istri Rusdi menunggu dengan gelisah sambil menenangkan anaknya yang berumur 7 tahun. Rusdi berjanji akan kembali membawa uang untuk mengobati anak mereka yang sakit tipus. Tapi, hingga hari menjelang malam, Rusdi tak kunjung pulang.
Jauh di pojok sel penjara yang dingin dan asing, Rusdi hanya berharap supaya bisa cepat pulang, setidaknya hanya membawa dirinya sendiri, sekalipun tanpa uang maupun kepastian.
Dalam tangis di hatinya ia setengah mati berharap agar anaknya tidak menganggapnya pengkhianat dan dapat melihat muka bapaknya di hari-hari paling kritis dalam hidupnya.
PENULIS MERUPAKAN MAHASISWa UNIVERSITAS BRAWIJAYA. saat ini aktif di divisi redaksi lpm perspektif.